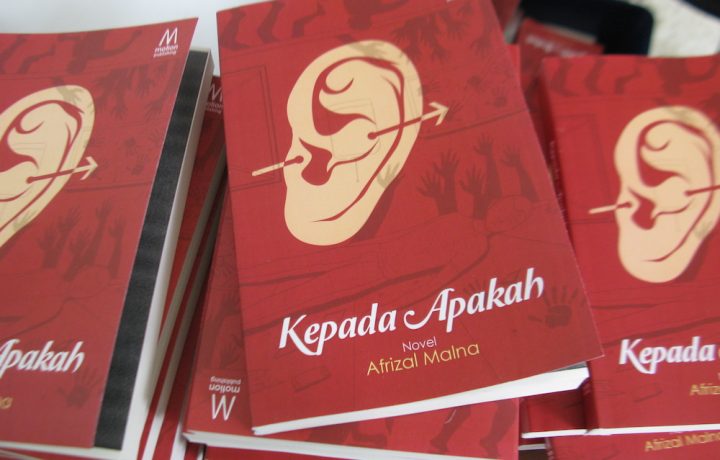I
Ketika Erói, kumpulan puisi karya Alexandra de Araújo Tilman tiba di tangan saya, terasa betapa ada lubang besar yang menganga di kepala saya. Lubang besar menganga itu katakanlah adalah pemahaman saya tentang sastra dan perpuisian negara sahabat terdekat—sekaligus negara yang kepadanya kita berhutang begitu besar, sebuah hutang yang tak akan bisa dibayar selamanya—sastra dan perpuisian Timor Leste. Betapa tidak, hanya ada dua buku kumpulan puisi penyair Timor Leste yang saya tahu dan miliki; Na luta contra o Colonialismo atau Iha Luta Hasoru Kolonialismu (2005) karya Fransisco Borja da Costa dan Erói yang terbit tahun ini. Yang lebih memperparah lubang tadi adalah bahwa dari buku pertama, saya tidak bisa menikmati sama sekali isinya. Buku karya Borja da Costa dimaksud diterbitkan dalam dua bahasa—Portu dan Tetum. Syukurlah, Erói bisa saya nikmati tidak lebih dari 50%-nya; buku ini menggunakan bahasa Tetum, Portugis, Inggris dan Indonesia.
Problem ketidakpahaman bahasa ini sudah lumrah di dalam hubungan antar negara, antar kebudayaan. Bagaimana ketika sesuatu berlabel ‘internasional’ jika dan hanya jika—atau tipis-tipis saja—ada enlish-englishnya. Alhasil, kita lebih banyak tahu karya-karya sastra/budaya negara dunia pertama, menyusul tipis-tipis negara-negara tingkat atasnya dunia ketiga, lantas menyusul dengan kecepatan sedang-sedang saja negara-negara berpengaruh tingkat regional. Tentu saja ada problem politik kebudayaan, saling silang pengaruh di dalamnya. Silahkan membuka buku yang barangkali statusnya sudah klasik semacam karya Joost Smiers, Art Under Pressure, untuk informasi lebih lanjut.
II
Pada 1990, Yayasan Obor Indonesia menerbitkan terjemahan sebuah buku kecil berisi tiga novelet karya penulis Papua Nugini, Percikan Api Fajar: Tiga Novelet Papua Nugini. Bagian akhir kata pengantar buku tersebut menarik untuk dikutip, “Semoga penerbitan karya-karya semacam ini akan memberi ilham kepada para penulis muda kita, agar juga mempunyai sikap demikian. Karena dengan mempunyai sikap dan pandangan yang bebas dari kompleks inferior minoritas, karya-karya kesusasteraan Indonesia akan menjadi menarik dan lebih bermutu.

Andai sejarah berjalan dengan cara yang berbeda, hanya andai-andai tapi, barangkali di tahun-tahun yang sama tersebut, Yayasan Obor Indonesia juga menerbitkan terjemahan dari Bahasa Tetun, atau barangkali Portu, karya-karya sastrawan/penulis dari Republik Demokratik Timor Lorosae, sebuah negara yang proklamasi kemerdekaannya dibacakan oleh Xavier do Amaral pada 28 November 1975 di Dili. Sebagaimana diungkapkan Helen Mary Hill di dalam bukunya, Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae, proklamasi itu diawali dengan penurunan bendera Portugis sekaligus menyimbolkan berakhirnya kolonialisme Portugis di Timor Leste yang sudah berlangsung 4 abad. Nyatanya, sejarah berjalan seperti yang kita tahu sekarang; selepas kolonialisme Portugis, masyarakat Timor Leste mesti mengalami lagi kolonisasi berikut. Kali ini dilakukan oleh ‘sesama negara dunia ketiga’, Indonesia, yang mulai menginvasi negara itu sebulan setelahnya dan mendudukinya/menjajahnya hingga 24 tahun ke depan. Sebuah peristiwa yang oleh Peter Carrey disebut Kolonialisme Dunia Ketiga.
Hanya sembilan hari setelah proklamasi itu, secara besar-besaran tentara Indonesia menginvasi Timor Leste, tepatnya 7 Desember 1975. Banyak pejuang dan masyarakat Timor Leste yang gugur kala itu. Salah satunya Fransisco Borja da Costa. Nug Katjasungkana menuliskan hal itu dengan cara yang menarik. Saya kutipkan[1],
Dili, 7 Desember 1975. Belasan ribu tentara Indonesia mendarat dari laut dan udara. Pagi itu menjadi gelap, matahari terhalang pasuskan payung yang diterjungkan dari kapal-kapal terbang. Seorang laki-laki muda, kurus, berambut panjang berlari-larian. Tanganya membawa sebundel kertas ketikan. Kumpulan puisi yang diketiknya pada beberapa tahun terakhir.
Laki-laki ini, Francisco Borja da Costa, baru beberapa bulan kembali ke Dili. Ia pengurus pusat FRETILIN (Frente Revolusionaria de Timor Leste Independente, Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur) yang bertanggungjawab menyebarkan gagasan dalam kegiatan pembebasan nasional Timor-Timur. Bersama penyair-penyair lain, ia sehari-hari bekerja keras menciptakan puisi dan lagu memberikan ilham dan penjelasan kepada rakyat banyak
….
Tanggal 7 Desember, sembilan hari setelah proklamasi, tentara Indonesia melancarkan serbuan besar-besaran. Francisco Borja da Costa kepergok seregu pasukan parakomando. Ia pun ditangkap, kemudian disiksa dan dibunuh. Sang penyair gugur pada usia 29 tahun sambil membawa kumpulan puisinya.
Serbuan dan pendudukan militer Indonesia menghalangi pembebasan nasional rakyat Maubere. Namun api yang dikobarkan oleh Francisco Borja da Costa tidak berhasil dipadamkan. Sampai hari ini Kolele Mai, Foho Ramelau, dan lagu-lagu lain yang disebarluaskan oleh gerakan pembebasan nasional Timor Timur terus dinyayikan dibalik pintu-pintu tertutup rapat di knua-knua pedalaman Timor Timur, di lingkaran-lingkaran klandestine di kota-kota, di kalangan masyarakat Timor Timur di pengasingan (rock band Midnight Oil menyanyikan dan merekam Kolele Mai versi mereka sebagai ungkapan solidaritas). Tarian tebe-tebe ditampilkan pada demonstrasi-demosntrasi pemuda Timor Timur di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta menuntut tentara Indonesia pergi dari Timor Timur. Yang semua adalah tindakan kebudayaan rakyat yang sedang membentuk identitasnya sebagai bangsa.
Kebesaran dan pengaruh Borja da Costa kita tangkap pula di dalam puisi karya Alexandra de Araújo Tilman bertajuk “Kukenang Jasadmu Borja da Costa”. Sejauh membaca puisi-puisi Alexandra yang berbahasa Indonesia di dalam Eroi, saya menangkap sosok Borja sangat berpengaruh. Setidaknya nama Borja muncul juga pada puisi “7 Desember Sendu”. Di sana, Alexandra menulis[2],
Borja…
Kan kutelusuri jejakmu
Tuk pekikkan syairku
Nan mengetarkan urat nadi
Setiap insan diatas persada
Timor Lorosa’e
Tampak di dalam bait ini, Alexandra semacam ingin melanjutkan jejak perjuangan Borja (Kan kutelusuri jejakmu/Tuk pekikkan syairmu). Borja memang seorang pejuang-penyair/penyair-pejuang Timor Leste. Sebagaimana dituliskan Nug Katjasungkana di atas—kemungkinan besar Nug menuliskan itu sebelum referendum—beberapa syair gubahannya lantas dilagukan dan menjadi nyanyian rakyat yang populer. Salah satunya adalah “Foho Ramelu” yang juga kita temukan banyak tersebar di lirik-lirik puisi Alexandra. Berikut puisi tersebut[3],
Hei, Gunung Ramelau, Gunung Ramelau, hei
Apa yang lebih tinggi dari puncakmu?
Apa yang lebih besar dari keagunganmu?
Mengapa, Timor, kepalamu tertunduk, selalu?
Mengapa, Timor, anak-anakmu diperbudak?
Mengapa, Timor, anak-anakmu terkantuk-kantuk seperti ayam?
Mengapa, Timor, anak-anakmu tertidur seperti budak?
Bangun! Kaki gunung memutih
Bangun! Matahari baru telah terbit
Buka mata! Matahari baru memasuki desa
Buka mata! Matahari baru di atas negeri kita
Bangkit! Ambil tali kendali kudamu
III
Puisi sebagai perjuangan dan atau perjuangan sebagai puisi lekat betul dengan penyair Borja da Costa. Saya kira hampir setiap tempat yang memiliki sejarah perjuangan yang demikian akan melahirkan penyair dengan corak yang demikian ini. Puisi atau gubahan mereka diarahkan untuk membangkitkan semangat perjuangan atau yang berhubungan dengan perihal-perihal tersebut. Di Indonesia sendiri puisi-puisi yang demikian banyak muncul pada Angkatan 45[4].

Saya kira puisi-puisi Alexandra de Araujo Tilman sedikit banyak bisa kita lihat di dalam konteks puisi sebagai perjuangan dan perjuangan sebagai puisi yang demikian. Bukan berarti bahwa puisi-puisinya, terkhusus yang terhimpun di dalam Eroi ini, hanya membicarakan tema-tema seputar Timor Leste di bawah kolonisasi oleh negara dunia ketiga lainnya aka Indonesia. Ia juga memotret kondisi Timor Leste pasca referendum. Ada semacam semangat ‘revolusi belum selesai’ di dalam puisi-puisi (khususnya yang berbahasa Indonesia) di dalam buku Eroi ini.
Satu yang pasti, keberpihakan puisi-puisi ini jelas; berpihak pada rakyat Buibere, Maubere, dalam upaya melanjutkan perjuangan, sebagaimana tampak pada puisi “Menerpa Hari Esok”[5],
Genderang perang telah berlalu
Menggugah mati setiap insan untuk bersatu
Menerpa praha yang hadir silih berganti
Melenyapkan kemunafikan, kekejian
Kenistaan, kemelaratan dan ketidakberdayaan.
Wahai….
Buibere, Maubere
Lantumkan syair keabadian Foho Ramelau
Keadilan, kebenaran, ketulusan, cinta
Dan kasih sayang.
Mengapa, mengapa, mengapa?
Mengapa kita harus bungkam
Menyaksikan penindasan dan kekejaman
Mencekik rakyat jelata
Yang kian hari kian menyembalkan
Wahai saudaraku…
Jangan biarkan manusia berdasi
Bertengger diatas kereta kencana
Sementara kaum papah disudutkan.
Demikianlah… A luta continua***
[1] http://obraoinoin.blogspot.com/2011/01/budaya-1.html. Aslinya dipublikasikan di majalah Media Kerja Budaya, November – Desember 1999.
[2] Alexandra de Araújo Tilman, Erói, (Salatiga: Widya Sari Press), 2022, hlm. 22.
[3] Helen Mary Hill, Gerakan Pembebasan Timor Leste, (Dili: Sahe Institute for Liberation & Yayasan HAK), 2000, hlm. 92 – 93.
[4] Meskipun Angkatan 45 di dalam konteks puisi Indonesia bisa diperdebatkan lebih lanjut. Semisal, Angkatan 45 yang istilahnya muncul pertama kali pada tulisan Rosihan Anwar ini, apakah benar-benar masih bersemangat serupa ketika ia muncul kembali di dalam ‘pengkultusannya’ oleh HB Jassin? Atau apakah semangatnya benaran sudah mati bersama peristiwa Madiun sebagaimana dituliskan Yogaswara aka AS Dharta?
[5] Alexandra de Araújo Tilman…, hlm. 94.
*Catatan: Dibuat sebagai bahan pendamping diskusi dalam rangka pembacaan dan peluncuran buku kumpulan puisi Erói karya Alexandra de Araújo Tilman yang diterbitkan oleh Penerbit Widya Sari Press, 2022. Pembacaan dan peluncuran Erói ini diadakan dalam rangka Jakarta International Literary Festival 2022. Saya diundang oleh Komunitas Danarto Dkk., Yogyakarta.