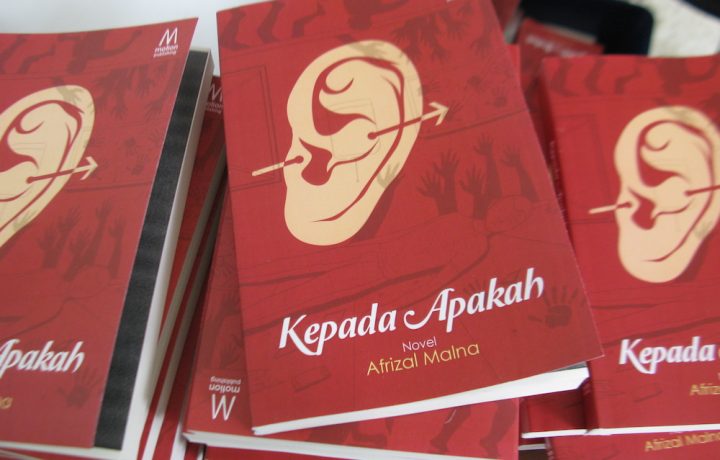Sejauh ingatan saya yang pendek, “Kesaksian Ganja Kering Basah Air Mata” adalah cerpen Martin Aleida yang pertama kali saya baca. Tentu saja saya membacanya ketika pertama kali muncul di laman Harian Kompas di hari minggu, tepatnya 13 Oktober 2003 silam. Kesedihan dan keterlibatan Martin Aleida pada permasalahan bangsa dan mereka-mereka yang tak beruntung melalui karya-karyanya tak perlu kita ragukan lagi. Martin Aleida, penulis kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 31 Desember 1943, pada awal 2019 lalu menerbitkan kumpulan cerpen Kata-kata Membasuh Luka melalui Penerbit Buku Kompas. Saya kira, inilah buku termutakhir Martin Aleida setelah pada 2017 dia menerbitkan Tanah Air Yang Hilang: Wawancara dengan Orang-orang “Klayban”, juga diterbitkan oleh penerbit yang sama.
Barangkali kebanyakan dari pembaca mengidentifikasikan Martin Aleida sebagai penulis dengan spesialisasi permasalahan 1965; khususnya keberpihakan pada korban dari G30S 1965 dan kejadian-kejadian setelahnya di dalam konteks itu. Pembacaan demikian ini mendapat legitimasinya lantaran Aleida sendiri adalah salah satu dari para korban itu. Bagi saya, jika bercermin pada cerpen-cerpen Aleida di dalam Kata-kata Membasuh Luka, pembacaan seperti ini tidaklah tepat. Memang, cerpen-cerpen di dalam buku ini banyak membicarakan perihal 1965. Namun, kita mesti membaca Martin Aleida lebih luas dari itu. Tentu saja bukan berarti perihal 1965 tidaklah penting. Martin Aleida sendiri pun mengakui bahwa untuk itulah dia menulis. Di dalam Tanah Air yang Hilang—buku tentang kisah para eksil 1965—kita jelas menemukan itu. Aleida menulis demikian di sana, “kepada mereka ingin saya sampaikan bahwa penguasaan kata-kata saya jelas tidak memadai untuk menangkap semua gejolak dan dambaan mereka sebagai orang-orang yang terbuang. Namun, simpati, kesetiakawanan, dan keberpihakan saya menjulang buat mereka semua. Karena itu dan untuk itu saya menulis” (Aleida, 2017).
Pembacaan atas Martin Aleida yang lebih luas ini akan saya mulai dengan “Kesaksian Ganja Kering Basah Air Mata” (hal. 161-170). Pemilihan itu bukanlah lantaran di dalam cerpen tersebut sajalah pembacaan atas Martin Aleida yang lebih luas itu bisa kita dapatkan. Alasan saya lebih sederhana dari itu; “Kesaksian Ganja Kering Basah Air Mata” adalah cerpen pertama Martin Aleida yang saya baca dan mungkin karena alasan itu pulalah, cerpen tersebut yang paling terpateri di dalam benak saya.

***
“Kisah Ganja Kering Basah Air Mata” muncul kali pertama pada Oktober 2003. Narator cerpen itu adalah sejumput daun ganja kering yang tergeletak di meja, di sebuah kantor polisi. Ganja itu menyaksikan seorang gadis Aceh diinterogasi polisi. Bagaimana bisa seorang gadis Aceh dan sejumput ganja bisa tiba di kantor polisi? Tentu saja lantaran ganja adalah benda yang dilarang hukum.
Alkisah, gadis ini adalah mahasiswi jurusan Hubungan Internasional tingkat akhir. Di dalam upaya menyelesaikan tugas akhirnya, gadis itu mengirim surat kepada ayahnya di kampung untuk mengirimkannya uang sedikit lebih banyak dari biasanya lantaran kebutuhan untuk tugas akhir tersebut, ia butuh uang sedikit lebih banyak. Ayahnya kebingungan; di satu sisi dia bahagia karena jerih payahnya sedikit lagi membuahkan hasil, namun di sisi lain dia tak punya uang yang cukup. Keadaan yang demikian agaknya mendorong sang ayah berbuat nekat; dia mengirimkan anaknya ganja. Tentu saja dengan maksud agar ganja itu dijual anaknya untuk menutupi kebutuhan keuangannya. Tindakan sang ayah tampak sebagai tindakan yang naif. Betapa tidak. Pastinya kabar bahwa ganja membahayakan sudah dia ketahui. Hal itu tampak, misalnya, ketika sang ayah ditanya apa isi paketnya itu oleh petugas pos, ia menjawab berbohong, “Buku, sajadah” (hal. 167). Apakah sang ayah naif? Belum tentu.
Salah satu yang menonjol dari cerpen-cerpen Martin Aleida—dan saya kira juga hal ini ada pada penulis-penulis bagus dengan kepekaan politik yang baik lainnya—dia selalu menjangkarkan pengalaman individu yang spesifik di dalam konteks pengalaman kolektif. Hal itu sangat tampak pada cerpen “Kisah Ganja Kering Basah Air Mata”. Problem si gadis Aceh yang butuh uang dan ayahnya yang kesulitan mencari uang ditempatkan di tengah pusaran peristiwa sosial yang merentang di dalam sejarah. Si gadis bercita-cita hendak mengetahui alasan mengapa bangsanya begitu hina di mata dunia. Hal itu lantaran sejarah kelam yang dimulai sejak 1965, pembantaian Tanjung Priok, dan lain-lain. Sebuah ingatan kolektif dimunculkan dalam sebuah peristiwa kecil.
Sang ayah, di dalam konteks mesti menyiapkan uang untuk anaknya, ditempatkan di dalam konteks yang setali tiga uang, namun lebih bersifat kekinian. Keadaan Aceh di dalam cerita adalah Aceh yang tengah bersiap-siap menyambut Operasi Militer. Penanda waktunya jelas, sebagaimana narasi dari secuil ganja itu, “Dan, oh gadis kawanku, maka datanglah hari yang dia tunggu dengan penuh kecemasan itu, Senin, 19 Mei 2003” (hal. 168). Tanggal itu, kita tahu, adalah hari dimulainya Operasi Militer Indonesia di Aceh yang terus berjalan hingga kira-kira setahun. Di dalam cerita digambarkan bahwa, peristiwa pengiriman ganja oleh sang ayah ke anaknya terjadi beberapa saat sebelum itu. Tentu saja, sebagai sebuah wilayah yang tengah dirongrong perkara yang demikian itu ditambah ayahnya adalah seorang petani biasa, mendapatkan uang dalam waktu dekat cukuplah sulit. Kita bisa membayangkan bahwa mengirimkan ganja agar anaknya menjualnya bisa saja merupakan sebuah tindakan keputusasaan sang ayah.
***
Kisah-kisah di dalam Kata-kata Membasuh Luka memang tidak semuanya berbicara tentang 1965. Cerpen-cerpen Aleida sesungguhnya perlu dilihat, jika mau ditarik benang merahnya, adalah cerpen-cerpen yang berpihak kepada kemanusiaan. Akan tetapi, kemanusiaan Aleida bukanlah kemanusiaan buta. Kemanusiaan yang dielaborasi dan diangkatnya ke dalam cerita adalah kemanusiaan yang berkait kelindan bersama beragam permasalahan di dalam sejarah maupun kehidupan terkini. Dengan kata lain, kemanusiaan yang berusaha tegak di tengah segala dialektika perjalanan sejarah dan percaturan politik hari ini. Bolehlah saya simpulkan, kemanusiaan Aleida adalah kemanusiaan yang disadari betul harus diperjuangkan bukan kemanusiaan yang dianggap sebagai sesuatu yang terberi.
Kemanusiaan seperti itulah yang saya kira alpa pada karya-karya sastra Indonesia terkini, terkhusus dari kalangan penulis muda. Alih-alih masuk ke arah itu, jika kita membaca dengan lebih teliti karya-karya penulis muda kita, justru perihal individualitas—kemanusiaan yang saya maknai dari Aleida adalah kemanusiaan yang tumbuh dari kesosialan dan bukan berarti tidak ada jenis kemanusiaan lain di luar itu. Jika pun kita menemukan karya-karya yang kental dengan kemanusiaan, kemanusiaan di dalam karya-karya termutakhir itu cenderung menghamba pada keindividualitasan ketimbang diletakkan pada dialektika sosial yang hidup.
Hal ini setali tiga uang dengan slogan yang kerap diulangi oleh mereka yang katakanlah muda dan kritis hari-hari ini, yakni “di mana negara ketika saya sakit gigi?” Pada pandangan pertama, slogan itu barangkali baik-baik saja. Namun, persis karena kita tahu bahwa sakit gigi tidak mungkin terjadi tanpa penyebab, maka betapa mengherankannya kaum muda yang kritis itu ketika mengucap slogan di muka lupa menambahkan bahwa, “negara tidak melarang dirimu mengonsumsi coklat sebanyak-banyaknya.” Artinya, imajinasi perihal kemanusiaan pada para penulis muda sekarang setali tiga uang dengan imajinasi politik di kepala sejawat mereka di kalangan muda-kritis; jauh dari melihat masalah sebagai hasil perjuangan dan tidak menempatkan permasalahan di tengah dialektika yang lebih luas. Pada titik ini, patutlah kita belajar pada karya-karya Martin Aleida.
Dari tiga puluh lima cerpen yang ada di dalam Kata-kata Membasuh Luka, hanya empat belas cerpen yang langsung berkisah tentang 1965. Selebihnya, dua puluh satu cerpen, berkisah perihal beragam hal; mulai dari kisah tentang seniman yang terlupakan, cerpen “Suara”, hingga kedekatan batin seekor anjing peliharaan dengan tuannya, cerpen “Eric, Makanlah…” Penjelajahan Aleida dengan demikian tak perlu diperbincangkan lagi; begitu luas. Dari kisah-kisah kemanusiaan yang dekat dengan permasalahan politik hingga kisah-kisah kemanusiaan yang intim personal, namun menggemakan permasalahan kemanusiaan yang lebih luas lagi.
***
Kisah-kisah 1965 dari Martin Aleida pun khas. Dia lebih banyak berkisah tentang peristiwa-peristiwa setelah 1965, setelah pembunuhan, penangkapan, dan penahanan tanpa pengadilan, setelah para tahanan dilepaskan dari Pulau Buru, misalnya. Aleida membicarakan 1965 di dalam konteks setelah 1965. Setelah semuanya berlalu, setelah kehidupan berjalan begitu normal bagi orang kebanyakan dan para korban 1965 itu, selalu saja ada peristiwa-peristiwa kecil yang katakanlah menjadi momen penghenti laju kenormalan, membawa imajinasi kembali ke 1965. Kisah-kisah 1965 Martin Aleida dengan demikian adalah kisah-kisah pengingat. Ia berfungsi menghentikan laju keseharian kita—yang diwakilkan oleh tokoh-tokoh di dalam cerita itu tentu saja—dan memberi kita kesempatan untuk mengambil sebuah memori yang tertanam jauh di alam bawah sadar kita, sebuah memori yang berkolerasi dengan memori kolektif. Memori kolektif ini jauh tertanam di alam bawah sadar kita, persis karena ia direpresi oleh tatanan keseharian yang diciptakan selama Orde Baru. Sejenis memori yang oleh Walter Benjamin, meminjam dari Charles Baudelaire, disebut mémoire involontaire. Dengan mengidentifikasikan diri kita sebagai tokoh-tokoh di dalam cerpennya, maka kita tahu peristiwa yang terjadi di dalam cerpen tersebut bisa juga kita alami. Di bawah ini, saya akan membicarakan dua cerpen di dalam konteks itu. Tentu saja lagi-lagi, bukan berarti cerpen yang lain tidak penting untuk dibicarakan.
Tokoh aku di dalam cerpen “Ziarah Kepayang” (hlm. 1-8) adalah seseorang yang telah lama merantau, jauh dari kampungnya. Dia adalah seseorang yang dianggap/dituduh terlibat dalam peristiwa 1965. Karena itu, abang dan adiknya menyembunyikan dan menanam buku-bukunya. Ketika pulang ke kampungnya setelah 50 tahun, dia teringat pada Atoknya. Di dalam perbincangan dengan Atok itulah buku-buku yang adalah benda-benda saksi sejarah 1965 teringat kembali. Sang tokoh menyesali kenapa abang-abangnya tidak bisa mengingat di mana buku-buku itu disembunyikan. Namun, Atok yang bijaksana itu menasihatinya, “sudah dikubur bertahun-tahun, kertasnya sudah lumat. Untuk apa kau lagi itu? Bukankah buku itu sudah ikut mendewasakanmu?” (hlm. 8). Kalimat itu sesungguhnya bukan sekadar nasihat untuk merelakan buku-buku saja. Lebih dari itu. Kalimat tersebut menasihati untuk merelakan peristiwa yang diwakilkan oleh kenangan akan buku-buku itu, peristiwa 1965. Aleida tidak melanjutkan kisah. Dia berhenti pada nasihat Atok. Bisa saja, tokoh aku memang melupakan buku-buku itu, tetapi kisah di balik buku-buku itu pastinya akan selalu datang di dalam hari-harinya.
Perihal ingatan menjadi penting di dalam “Surat Tapol Kepada TKW, Cucunya”. Lebih jauh, cerpen itu ini menggugat seni, lebih khusus film dokumenter. Alkisah Feb, cucu kakek tapol itu, mengirimkan surat protes mengapa sebuah film dokumenter perihal tapol 1965 begitu sangat tidak menarik. Demikian Aleida menggambarkannya, “Tetapi, kau menyebutkan aku tak punya imajinasi. Majal…! Hatiku tidak terluka karena label yang kau tancapkan itu. Bagaimanapun, pedih membaca kata-katamu itu. Kau sebutkan tulisan yang kususun dengan berkeringat itu tak lebih dari catatan kerani kelurahan yang terus merengek minta gaji dinaikkan, sementara isi laporannya hanya mengotori halaman” (hlm.12).
Saya kira, pada kutipan terakhir ini Aleida sangat keras memarahi dirinya sebagai penulis. Namun, Aleida juga menggunakan kata “laporan.” Bagi yang terbiasa dengan narasi 1965, tentu saja tahu bahwa di sekitar ingatan akan peristiwa itu ada juga sangat banyak non-governmental organization (NGO, organisasi non-pemerintah) yang mengadvokasi perihal ini. Kata “laporan” persis dekat dengan dunia NGO. Maka, dengan sedikit imajinasi, Aleida—atau jika Aleida tidak memaksudkannya, sebagai pembaca kita sah menginterpretasikannya—sesungguhnya marah pada kerja-kerja NGO tersebut yang laporannya sekadar mengotori; tak bermakna, tak menghasilkan apa-apa.
Cerpen itu juga berjalan jauh; dia mengkritik seni dengan tema 1965. Meski hanya merujuk pada satu jenis seni, film dokumenter, kita bisa memperlebarnya. Demikian Aleida membicarakan film dokumenter itu, “Dan aku mati kutu ketika kau cecar, kau tekan terus, mengapa judul film yang semula begitu merangsang dan heroik tiba-tiba diganti dengan kata yang hambar, seakan-akan pulau penyiksaan itu sebuah surga lama yang baru ditemukan. Ada apa? Takut…? Menyensor diri sendiri?” (hlm. hlm. 11). Itu kata-kata yang begitu keras. Lebih jauh dari permasalahan mengkritik judul sebuah film, dia sesungguhnya mengkritik narasi 1965 diceritakan oleh film-film dokumenter. Dengan merujuk pada tulisan Anne Frank di bagian awal cerpen, sesungguhnya cerpen ini mau menggugat: mengapa tragedi di negeri ini tidak bisa menghasilkan sebuah karya seni yang besar dan menggugah sebagaimana tragedi di negeri-negeri lainnya?

Terhadap tuduhan tersirat Aleida itu, kita tentu saja bisa berkelit bahwa tragedi 1965 adalah tragedi yang dimenangkan oleh pemenang. Korban 1965 hingga kini adalah yang kalah. Di dalam konteks dunia yang lebih besar pun, dunia global, mereka yang diwakili oleh korban 1965 hingga hari ini adalah mereka yang kalah. Di dalam konteks itu, wajarlah bahwa karya-karya 1965 tidak bisa berangkat atau berprestasi jauh dari itu. Pramoedya yang begitu digdaya di dalam karya-karyanya pun hanyalah sampai dicalonkan sebagai peraih hadiah Nobel. Namun, itu Pramoedya; dia yang adalah korban dan dia yang adalah berkarya. Karya-karyanya pun tidak mengangkat 1965 sebagai latarnya—kebanyakan novel Pramoedya berlari jauh dari itu, dia mempertanyakan pendasaran negara-bangsa Indonesia.
Tuduhan Aleida persis pada diri sendiri sebagai penulis dan persis pada generasi setelah dirinya yang punya ingatan dan keberpihakan pada 1965. Sejauh apakah kualitas film-film—lebih banyak di dalam kasus 1965 adalah film dokumenter dengan keinginan advokasi yang kuat—dan karya-karya sastra—baik cerpen mau pun novel—yang dihasilkan hingga hari ini mampu menggugah pembacanya? Pertanyaan di sini bukan pada perkara sosiologisnya—pasar dan pembaptisan atau kuratorial misalnya—tetapi pada kualitas artistik itu sendiri. Sejauh ini memang jika diperhatikan karya-karya di dalam konteks itu lebih banyak mengedepankan keberpihakan tanpa terlalu serius menggarap bentuknya. Padahal, karya seni yang baik justru adalah kesamaan di antara kedua itu; bentuk yang baik akan menyinarkan keberpihakan yang dititipkan senimannya.
Dengan kata lain, seniman-seniman kita sejauh ini gagal menghasilkan bentuk yang “indah”. Yang ada pada mereka hanyalah keterkejutan dan “rasa kasihan” pada 1965. Berhenti sampai di situ; tak lari jauh dari itu. Itulah sebabnya mengapa Joshua Oppenheimer dengan dua film dokumenternya begitu membius. Sejauh ini, bentuk yang ditawarkan Joshua jauh melampaui bentuk-bentuk yang ada pada seniman-seniman kita. Sedangkan isi dan keberpihakannya sesungguhnya sama. Seniman-seniman kita tentu harus belajar lebih banyak lagi. Persis seperti yang saya katakan di atas. Imajinasi politiknya perlu dilatih lagi. Jangan sampai sekadar menjadi bocah kampung yang melempar batu ke tangsi tentara; digertak sedikit oleh penjaga, menjerit-jerit soal ketidakadilan, menggantungkan harapan pada ide-ide abstrak yang dianggap terberi begitu saja; bukan melihat ide-ide itu sebagai buah perjuangan. Mengapa tidak, karena sudah terlalu lama bersikap seperti pemuda kampung dengan kenakalan a la kadarnya itu, mencoba menyaru dan masuk ke dalam tangsi tersebut?
***
Saya kira dengan membaca Kata-kata Membasuh Luka kita seharusnya tidak sekadar berhenti pada kenikmatan cerita—ini level pembaca biasa—tetapi juga kita mesti menangkap semangat kemanusiaan dengan kesadaran pada silang sengkarutnya dengan keadaan negara-bangsa dan dunia pada umumnya; sebuah cara baca yang lebih dewasa. Pelajaran-pelajaran yang ditawarkan Aleida sesungguhnya melampaui gaya realisnya serta bahasa khasnya yang terus menggugat. Lebih dari itu, keluhan Aleida di bagian awal “Surat Tapol Kepada TKW, Cucunya” mestinya menjadi tamparan bagi semua kita yang merasa punya keterlibatan pada 1965, yang merasa kerap tersentuh mémoire involontaire-nya. Ketika memori kolektif di dalam diri Anda itu tersentuh, Anda harus segera dengan sungguh-sungguh menangkapnya, memahami semangat dari masa lalu itu di dalam diri Anda, dan memperjuangkannya dengan seserius mungkin alias bukan sekadar melempar kerikil ke atap tangsi lalu menangis minta keadilan ketika digertak penjaga. Namun, jika Anda memang tidak punya imajinasi perihal kolektivitas yang merentang di dalam sejarah, apa pun bacaannya, apa pun tontonannya hasilnya jelas; menemui ruang hampa di dalam kepala.***
Data Buku:
Judul: Kata-kata Membasuh Luka (Kumpulan Cerita Pendek)
Penulis: Martin Aleida
Penerbit: Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2019
Tebal: xii + 340 halaman
ISBN: 978-602-4126-13-1
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Jurnal Prisma, No. 2, Volume 38, 2019.