Sudah lebih dari empat dekade berlalu semenjak terjadinya G30S. Inilah peristiwa yang menurut banyak pengamat dan sejarawan Indonesia adalah tonggak penting perjalanan bangsa ini pasca kemerdekaan. Wacana 1965 sampai saat ini terkesan terus digarap, tak putus-putusnya dibincangkan, dibaca ulang, ditulis ulang, seperti yang terjadi dengan tulisan ini, sehingga terkesan membosankan dan menjenuhkan untuk segelintir orang.
Peristiwa yang “menekuk-lututkan” partai komunis terbesar dunia di luar Uni Soviet dan RRC waktu itu pada hematnya harus dilihat sebagai trilogi; peristiwa G30S dengan segala versinya, pembantaian 1965, dan pembuangan Pulau Buruh serta para eksil di luar negeri (Warman Adam, 2004). Sejak itulah, di bawah kaki Orde Baru, “kiri” menjadi sesuatu yang diharamkan di negeri ini sekaligus menjadi ‘pembunuh’ menakutkan baik bagi para pemeluknya mau pun bukan.
“Kiri” versi rezim penguasa, “kiri” yang membunuh para jenderal dan berusaha mengkudeta lama nian bercokol di ingatan kolektif bangsa sebagai sebuah kebenaran. Ingatan kolektif yang terseleksi sesuai keinginan penguasa dan parsial ini melupakan, menutup mata atau menutup pintu rapat-rapat untuk versi-versi berbeda, entah versi para korban mau pun versi saksi mata kala itu. Rakyat negeri ini pun begitu lamanya mengidap amnesia sejarah. Goebbels, seorang Nazi Jerman, pernah berujar, ceritakan sebuah tipuan berkali-kali, niscaya akan menjadi kebenaran. Mungkin seperti itu yang terjadi di negeri ini.

Demi melawan penyakit amnesia sejarah, tidak bisa tidak, versi sejarah yang dahulunya dibungkam harus diberi tempat, terus diperbincangkan, dibaca ulang, dan ditulis ulang. Dia tidak boleh membosankan bila belum semua kita terbebas dari penyakit itu, bila belum semua kita mengakui kesalahan masa lalu. Dalam usaha itu, sastra pun turut andil, memberi arti berbeda pada amnesia sejarah ini. Sastra dalam perbincangan ini menjadi penting bukan hanya karena keterlibatan pengarang pada perubahan atau peristiwa sosial tertentu, melainkan juga karena sebuah karya berkolerasi dan saling melengkapi dengan situasi sosial di luar dirinya. Inilah yang ditanggapi cerpen-cerpen karya Linda Christanty, Agus Dermawan T, dan Imam Muhatron (untuk menyebut beberapa nama). Karya mereka yang mengangkat ihwal peristiwa 1965 dalam seliweran kegairahan prosa Indonesia sejak 1998 menjadi menarik untuk diamati.
***
Beberapa cerpen yang menyinggung peristiwa 1965 yang sempat singgah di pembacaan saya menonjolkan sisi ingatan korban orang kedua (mereka yang tidak menjadi obyek dalam penangkap mau pun pembantaian). Tamu (Kompas, 20 Juni 2004) karya Ratna Indraswari Ibrahim, Kami Bongkar Rumah Kami (Suara Merdeka, 15 Juli 2007) karya Imam Muhtarom dan Candik Ala (Kompas, 30 September 2007) karya GM Sudarta misalnya mengungkit perihal korban tak langsung prahara itu.
Ayah dari Dara dalam Tamu dibawa pergi beberapa orang pada 7 November 1967 tanpa alasan yang jelas dan tak pernah kembali lagi. Sebagai seorang Kabag, Papa Dara tidak terlibat partai apa pun. Ia pun bukan orang yang fasih dan penganut kiri. Buku-buku berhaluan kiri titipan Om Daryo di rumah pun sudah dibakar. Tamu memperlihatkan bahwa siapa saja, kiri mau pun bukan, bisa dibawa pergi dan tak pernah kembali pada fase pembantaian 1965. Kenangan akan ayah yang dibawa pergi dan tak pernah kembali menjadi kenangan teramat menggetirkan bagi Dara dan dara-dara yang lain.
Dalam Kami Bongkar Rumah Kami yang mengangkat tokoh generasi ketiga dari sebuah keluarga, rumah menjadi saksi kesengsaraan keluarga besar sang algojo di pembantaian 1965. Semenjak salah satu anggotanya menjadi Sang Pembelih, rumah itu tak urung dirundung malang. Betapa tidak. Selain seluruh penghuni rumah, kecuali Sang Pembeli atau Pak Min, menanggung beban moril, mereka pun harus menghadapi kesintingan Pak Min. Ketika suara-suara sayatan 1965 menghantui lagi Pak Min di tahun 1980-an, ia akan mencari apa saja, membuat kegaduhan bagaimana saja, sampai ada suara-suara teriakan yang mendiamkan suara sayatan yang menghantuinya. Pada 2006, generasi yang mendiami rumah itu pun berinisiatif merenofasi rumah itu. Mereka pun berencana membangun sebuah taman dengan pohon-pohon cemara untuk menggantikan pekarangan yang tak terurus dengan sepuluh pohon kelapanya agar, “…mengingatkan kami bahwa kami hidup pada tahun 2006 dan bukan berada di tahun 1967…”
Rupanya peristiwa di 1967 bukan saja menyisahkan kegetiran bagi Dara yang ayahnya dibawa pergi dan tak pernah kembali, tetapi juga menyesakan dan menghantui keluarga besar Pak Min sang eksekutor. Keduanya mencandrakan bagaimana peristiwa seputar 1967 tidak memberikan keuntungan apa-apa untuk siapa pun. Yang mengeksekusi dan yang dieksekusi sama-sama menderita. Tetapi, tentu saja ada yang memancing dan mendapat untung di air keruh.
Dalam Pesta Terakhir (Koran Tempo, 21 Desember 2003) karya Linda Christanty, ‘yang mengeksekusi’ dan ‘yang dieksekusi’ menjelma satu tubuh; dalam tokoh Lelaki Tua. Dari tahanan politik peristiwa 1965 di Penjara Salemba, ia menjelma seorang juru catat yang menjebloskan teman-temannya ke penderitaan yang lebih parah. Dari menderita di penjara, hidupnya berubah menjadi begitu penuh materi karena kerja spionasenya itu. Namun di hari tuanya, Pak Tua merenungkan kembali perjalanannya dan menyesali diri. Ia hendak membuat pengakuan pada Mursid, sesama aktifis Lekra yang dijebloskan ke penjara waktu itu. Namun sayang, sebelum hal itu tercapai, cucunya mengalami kecelakaan. Lelaki Tua pun berlari menyelamatkan cucunya dan tak sempat membuat pengakuan. Betapa peristiwa 1965 menyimpan begitu banyak teka teki kecil dan misteri-misteri kecilnya yang bisa saja tak akan pernah terungkapkan.
Cerpen Sejumlah Konon di Rumah Loteng (Suara Pembaruan, 15 Juli 2007) karya Agus Dermawan T bagaikan puzzle kenangan dengan bongkar pasang kisah yang berganti-ganti. Setiap kisah dihiasi konon. Misalnya, “…konon pada bulan Agustus tahun 1942”, atau, “…sampai akhirnya datang ke telingaku sebuah konon yang lain”. Dengan menggunakan kata konon, kisah-kisah kecil akibat gejolak sosial politik negeri ini menjadi ‘isapan jempol’ semata, bukan sebuah realitas sejarah yang harus serius digarap. Begitu juga konon lain yang mengisahkan, “… Pada bulan Desember 1965 rumah itu tiba-tiba digedor-gedor sekelompok orang. Dikatakan oleh orang-orang tersebut bahwa si penghuni rumah menyembunyikan seorang buron di atas loteng”. Maka, bisa saja begitu lama cerita getir tentang para korban peristiwa-peristiwa berdarah di negeri ini, seperti para penghuni Rumah Loteng yang berganti-ganti itu, hanya menjadi sebuah ‘konon’, semacam dongeng pengisi waktu senggang.
Berat Hidup di Barat (Kompas, 9 Mei 2004) karya sastrawan eksil Soeprijadi Tomodihardjo menceritakan kisah Eric Sullivan, seorang eksil dari Addis Ababa, Ethiopia. Eric Lewat tokoh aku diceritakan mengalami adaptasi yang setengah-setengah di lingkungan barunya, sebuah flat di Jerman(?). Akibatnya, gaya hidupnya dan kebiasaannya yang berbeda dengan orang-orang sekitar membuat keluarganya dikucilkan. Eric Sullivan sebenarnya adalah proyeksi kehidupan tokoh aku sendiri yang adalah seorang eksil Indonesia. Sesuai judulnya, Berat Hidup di Barat, cerpen ini menggambarkan bagaimana sulitnya para eksil di luar negeri memulai hidup baru di tanah baru, jauh dari lingkungan asalnya. Namun mereka tetap bertahan, seperti Eric Sullivan yang sampai kini masih tinggal di flat itu dengan anaknya yang kini sudah lima orang.

***
Karya sastra selalu mengiringi setiap perubahan sosial dan masyarakat. Walau pun jarang menjadi narasi besar dalam kehidupan, sastra selalu turut mewarnai, merefleksikan, memberi nilai pada kehidupan dan perubahan kehidupan itu sendiri.
Cerpen-cerpen yang disebutkan di atas tidak mengangkat tokoh-tokoh besar, para pelaku sejarah yang menjadi kanon. Seorang pegawai negeri kecil (Tamu), seorang pengkhianat yang resah di masa tua (Pesta Terakhir), para penghuni rumah loteng (Sejumlah Konon di Rumah Loteng), seorang penjagal dan keluarga yang menanggung malu (Kami Bongkar Rumah Kami) adalah mungkin tokoh-tokoh kecil yang cepat terlupakan kehidupan. Namun melalui cerpen-cerpen ini, kita diingatkan bahwa perjalanan bangsa pernah mengorbankan mereka. Karena pada dasarnya, sastra yang fiksi itu merefleksikan dan menyiratkan serta menyuratkan apa yang pernah, sedang dan akan terjadi.
Peristiwa-peristiwa kecil yang menghiasi prahara 1965 di pelosok-pelosok desa dan kampung sering hanya menjadi ‘konon’. Melalui karya-karya sastra, sadar atau pun tak sadar, peristiwa-peristiwa kecil itu masuk ke benak kita dan menyadarkan kita akan kerja renovasi yang belum dilakukan, yang belum dirampungkan. Arkian, kesalahan-kesalahan masa lampau harusnya tak pernah lagi ada, amnesia sejarah mestinya disembuhkan secepatnya.***
*Catatan: Tulisan ini dipublikasikan pertama kali di media populer alternatif PendarPena Nomor 10, Tahun Pertama, September 2008.



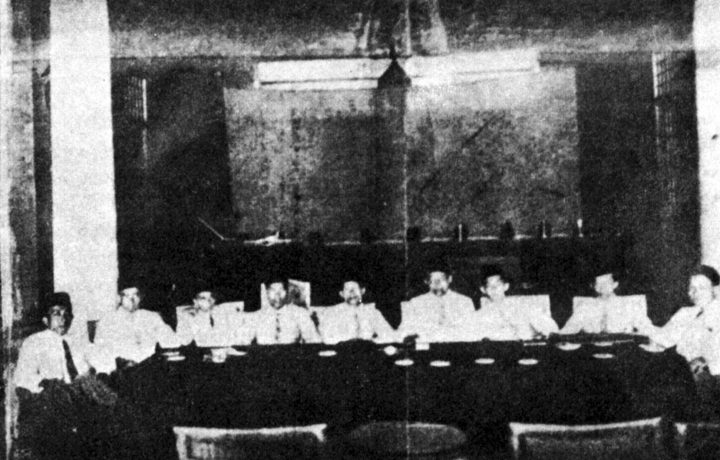
Pingback: Esai Berto Tukan “Mengcongkel Selilit Ingatan” dan Sekumpulan Cerpen-cerpen ’1965’ – Perpustakaan Online Genosida 1965-1966
Pingback: ‘Berat Hidup di Barat’ : Kisah Eksil ’65 (Jurnalis dan Cerpenis) Soeprijadi Tomodihardjo. *simak Arsip Beberapa Cerpen dan Artikelnya di Kompas, Sinar Harapan dan Jawa Pos – Perpustakaan Online Genosida 1965-1966