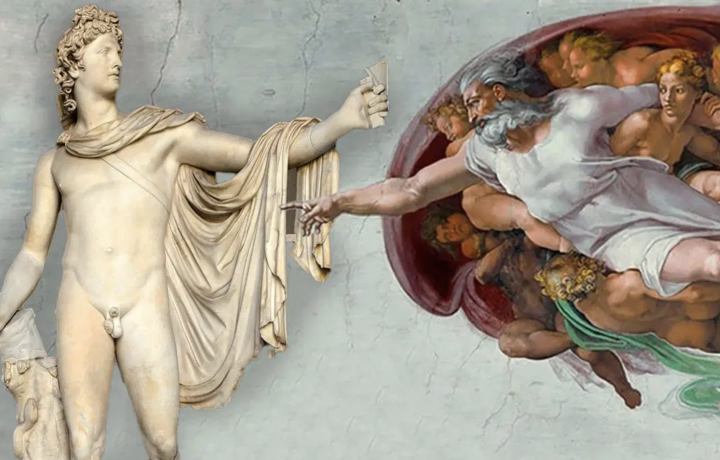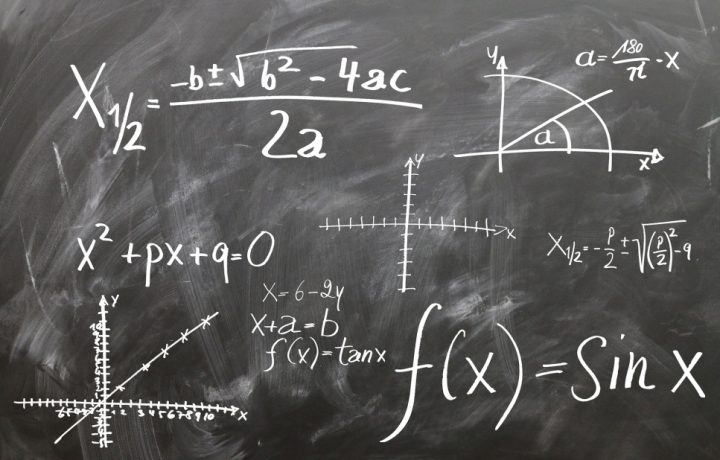Musim hujan sudah mengetuk pintu Jakarta. Dan ini bukan tamu yang ditunggu dengan suka-cita. Bagi mayoritas orang Jakarta, hujan adalah kutukan. Ketika musim hujan tiba, segala iba dan belas-kasih tercurah ke kota ini. Dari kerabat, kawan yang ada di luar Jakarta atau pendatang baru, atau para pengunjung sesaat. Setiap ada berita tentang banjir di salah satu kelurahan di Jakarta muncul di televisi, orang tua di kampung—bukan orang tua saya tentu saja—cepat-cepat menghubungi ponsel anaknya yang sudah 7-8 tahun hidup di Jakarta. Tentu untuk menanyakan kabar. Dan sang anak kerapnya—juga bukan saya—marah-marah lantaran setiap tahun dia harus menjelaskan hal yang sama kepada orang tuanya; banjir di Jakarta itu lumrah, selumrah petani ladang tadah hujan membersihkan kebunnya ketika hujan pertama tiba. Tentu kita harus berhati-hati dengan kata lumrah ini. Dan keberhati-hatian kita ini, alhamdulilah, membantu saya untuk sekali lagi menunaikan kewajiban menulis pada rubrik ini dua minggu sekali.
I
Bagi pembaca yang sering mengikuti perbincangan-perbincangan seputar banjir Jakarta, saya sarankan untuk setelah selesai dengan kalimat ini langsung meloncat saja ke bagian II tulisan ini. Sungguh, saya akan mengulangi hal-hal yang sudah anda ketahui. Saya akan memulainya dari sebaris lirik lagu Piknik 72 dari grup Naif, ‘makan roti buaya / Dengar lagu kita.’ Nah, roti buaya memang simbol kesetiaan dua pasang kekasih, lebih jauh suami-istri dalam kebudayaan Betawi. Saya sendiri sudah lupa dari mana saya mendapatkan informasi ini. Dari sini jugalah muncul julukan buaya darat bagi mereka yang dianggap tak setia. Buaya adalah makhluk air yang setia pada satu patner hidup saja seumur hidupnya. Maka, buaya yang berpindah pasangan tidak bisa tidak buaya yang tidak hidup di air.
Jelas metafora dan simbol buaya tidak muncul dari sebuah masyarakat yang hidup di padang gurun. Masyarakat Betawi hidup di Sunda Kelapa aka Jayakarta aka Batavia aka Jakarta. Kota ini adalah kota dengan sejuta sungai dan rawa. Barangkali, di suatu masa jauh sebelum Fatahilah dan VOC mampir ke kawasan ini, jumlah buaya sama banyak dengan jumlah manusia. Jan Pieterszoon Coen rupa-rupanya begitu rindu rumah ketika tiba di kota ini. Ia, pada 1620, membangun Batavia di tepi Sungai Ciliwung. Tata kota pun ia sama-samakan dengan kota-kota di Belanda yang memang akrab dengan air. Pelancong-pelancong Eropa yang berkunjung ke Batavia di akhir abad 17, menggambarkan kota ini sebagai kota yang indah dengan kanal-kanal teratur dan parit-parit lurus berpagar tanaman hijau. Malarialah yang lantas membuat pusat Batavia pindah ke wilayah sekitaran Monas sekarang (Ahsan, 2008). Seandainya saja saya hidup di Jakarta beberapa puluh tahun silam, barangkali saat ini saya sedang indehoy di atas sampan yang melaju di atas sungai nan tenang. Setidak-tidaknya, cuplikan kisah itulah yang paling saya ingat dalam Ca Bau Kan, novel sejarah Remy Sylado. Sayang, yang tersisa pada kita hanyalah jembatan di atas kali kotor yang selalu bergetar ketika bus melaluinya atau aroma tak sedap yang sesekali tercium ketika tengah mengantri di halte Transit Bus Transjakarta di Harmoni.
Nah, dengan rentang sejarah yang demikian, lumrah bukan jika sang anak yang menerima telepon dari orang tuanya di kampung, menganalogikan banjir Jakarta dengan petani tadah hujan yang otomatis membersihkan ladangnya ketika hujan pertama curah?
II
Hujan pertama untuk musim hujan Jakarta kali ini, bagi saya, adalah gerimis yang terjadi pada Selasa dini hari (12/11) lalu. Ketika itu, saya dan dua kawan, sedikit berjalan sempoyongan di Kabel Atas, Rawasari, Jakarta Pusat. Hari itu memang cukup melelahkan. Setelah dari kegiatan kami masing-masing yang meletihkan, kami menghadiri Pidato Kebudayaan DKJ yang dibawakan Ibu Karlina Supelli. Barangkali kini pembaca sekalian bisa dengan mudah menemukan poster berisi 8 Pokok Siasat Kebudayaan, usulan dari Pidato Kebudayaan DKJ itu di media sosial.
Gerimis menimpa kepala kami yang mulai ‘keleyengan.’ Sialnya, Kabel Atas di antara tengah malam dan fajar hari mengandaikan semua penghuninya gemar melompati rintangan. Beberapa bulan lalu setelah semakin marak curanmor di wilayah itu dan juga beberapa insiden menyangkut balapan liar, gang-gang sempit di sekitaran Kabel Atas pun ‘diportal’ setinggi perut orang dewasa. Kami pun memanjatnya, membiarkan bagian tubuh di sekitar paha sedikit perih. Bunyi air mengalir di selokan berbaur bau makanan sisa dari warteg yang barangkali kurang laku ditimpa aroma debu yang melumpur serta langkah sempoyongan kami menjelma simponi malam. Beberapa meter di depan kami, ada pengkolan tanpa penerangan. Bunyi dengkur samar-samar terdengar. Semakin kami melangkah maju bunyi itu semakin kentara. Ketika berbelok ke kanan, kami temukan seorang pria 60-an tahun hitam gempal dengan rambut putih tipis di kepalanya berbaring nyenyak di atas sofa tua dengan bolong sana sini yang diletakan di samping gang itu, tepat di tepi selokan selebar 50-60an cm. Ada terpal biru menaunginya memang. Ah, saya tak mau menerka-nerka mengapa pria itu tidur di sana.
‘Kira-kira Bapak tadi sedang bersiasat atas apa ya?’ Tanya salah satu kawan, tentu saja berkelakar, setelah kami melangkah cukup jauh.
‘Ah, barangkali itu belum setingkat siasat. Ia baru sekadar ‘ngakalin’ aja,’ timpal kawan yang lain, entah berkelakar entah serius.
Siasat memang cukup familiar untuk saya akhir-akhir ini. Selain 8 Pokok Siasat Kebudayaan tadi, Jakarta Biennale 2013 pun mengangkat tema Siasat. Dengan tema ini Jakarta Biennale hendak melihat kembali dengan lebih kritis praktik-praktik warga kota (Jakarta) dalam menyiasati kehidupannya di kota ini (Darmawan, 2013). Maka, berhamparanlah perkara kehidupan urban, kendaraan, macet, kampung kumuh, dan masih banyak lagi di Pelataran Parkir Teater Jakarta, venue Jakarta Biennale yang sudah sempat saya kunjungi. Malam ini tiba-tiba saya sadar selilit apa yang ada di benak ketika memperhatikan karya-karya di sana. Sejauh yang saya amati, tak satu karya pun yang merespons perkara banjir yang akarnya ada pada geografis Jakarta; sungai dan rawa-rawa. Padahal perkara banjir dan juga malaria ini-lah yang barangkali umurnya setua umur kota Jakarta itu sendiri.
Musim hujan mulai turun di Jakarta. Tapi tak selalu hujan menyedihkan. Setidaknya ‘…eh hujan gerimis aje…’ selalu memperdengarkan suara yang ceria.***
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Rubrik Oase IndoProgress, 17 November 2013.