Kini, kita hidup bersama internet. Sadar atau tidak, internet mengubah perilaku manusia. Dari berbelanja, mencari hiburan, berpolitik, menciptakan citra diri, mencari pengetahuan, bahkan juga bercinta, hampir semuanya bisa atau kerap kali dilakukan melalui media internet. Bahkan, perkembangan teknologi komputer dan internet mutakhir sudah memungkinkan untuk menciptakan sentuhan tubuh secara maya. Salah satu contohnya peranti lunak bernama kissenger. Peranti ini memungkinkan dua orang yang berada di tempat yang berbeda merasakan ciuman yang nyata. Kegiatan-kegiatan yang dahulunya mengharuskan orang mendatangi tempat-tempat lain dan berinteraksi langsung dengan manusia lain, kini bisa dilakukan dari rumah melalui internet.
Kemunculan dan semakin meluasnya penggunaan internet membuka kemungkinan baru dalam tingkah laku sosial di Indonesia. Sejak awal kemunculannya di akhir ‘90-an, internet berandil signifikan terhadap beberapa peristiwa di Indonesia. Ia telah digunakan dalam ‘perlawanan’ terhadap otoritarianisme Soeharto. Hill dan Sen mengajukan salah satu argumen perihal peran media dalam runtuhnya Soeharto, yaitu perubahan bentuk media dan konsekuensi kebudayaan yang diakibatkannya secara global merusak dua alat penting pemerintah Orde Baru atas media, yakni propaganda dan sensor. Pemerintah kala itu belum terlalu sadar dengan keberadaan media komunikasi yang satu ini.
Kini, penggunaan internet di Indonesia semakin ramai. Portal-portal berita, website-website pun bermunculan bak jamur di musim hujan. Banyak pula berguguran dan diganti dengan yang lain. Namun, ada pula yang bertahan dan makin digdaya. Pengguna pelbagai media sosial semakin bertambah dari hari ke hari. Satu media sosial berganti dengan media sosial lainnya dengan pelbagai ekspresi penggunaannya: dari perayaan narsistik hingga penggalangan dukungan untuk kegiatan sosial tertentu. Perkembangan teknologi internet yang demikian di satu sisi disambut dengan penuh sukacita dan di lain sisi merisaukan dampak-dampak negatif yang dibawanya. Bak Janus, salah satu dewa dalam mitologi Romawi, ia memiliki dua wajah dengan rupa bertolak-belakang: di satu sisi indah rupawan dan di sisi yang lainnya jelek menakutkan.
Tentu, sebagaimana semua kemajuan di negeri ini, kemunculan internet di Indonesia di paruh kedua ‘90-an tak terjadi secara merata. Hanya kota-kota besar di Indonesia saja yang merasakannya. Data Kominfo tahun 2010 menunjukkan bahwa 67 persen distribusi komputer dan 70,05 persen akses internet terkonsentrasi di Jawa dan Bali, sementara sebagian besar daerah lain masih tertinggal. Ketersediaan warnet atau kios internet pun setali tiga uang; masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Jawa, Bali, Sumatera, dan ibu kota-ibu kota provinsi lainnya. Bahkan bisa jadi beberapa alat komunikasi yang sempat muncul di Indonesia tidak pernah dirasakan oleh mereka yang tak tinggal di kota-kota besar. Pager misalnya, pada hemat saya tak dirasakan oleh masyarakat di luar kota-kota besar. Paling-paling mereka mengetahui keberadaan benda tersebut entah melalui iklan atau lagu yang dibawakan grup band NEO.
Pesawat telepon—alat komunikasi yang sekarang bisa kita sebut ‘jadul’ itu—pun bukan berarti merata penggunaannya di seluruh Indonesia. Seingat saya, di era ‘90-an, penduduk-penduduk desa di Provinsi NTT misalnya, terkadang perlu ke ibu kota kecamatan atau kabupaten dan menginap semalam di sana hanya untuk menerima telepon dari sanak saudaranya yang merantau di kota-kota besar di luar NTT. Biasanya, keluarga di—sebut saja misalnya Jakarta—menelepon ke nomor telepon keluarga yang ada di kota kabupaten dan mengadakan janji kapan akan menelepon saudara yang tinggal di desa (tentu saja beragam jarak antara desa dan kota kabupaten). Lantas keluarga di kota kabupaten tersebut mengirim surat perihal waktu yang ditetapkan tersebut ke desa. Seingat saya, perubahan baru terjadi di awal ‘2000-an ketika pesawat-pesawat telepon masuk ke desa-desa dan wartel desa mulai dikenal. Kala itu, penduduk kota-kota besar di Indonesia sudah mulai berasyik masyuk dengan internet. Agaknya hal ini berkat program pemerintah yang kala itu bertajuk “Desa Dering dan Desa Pintar”. Apa yang terjadi dengan pesawat telepon di awal ‘2000-an itu, kini, terjadi pula pada komputer dan internet.
Nir-kabel Masuk Desa
Seorang kawan lama dari wilayah timur Indonesia pada suatu waktu berkunjung ke Jakarta. Di dalam sebuah kesempatan, ia meminta saya untuk membuatkannya akun Facebook. “Kebetulan bersua, daripada harus membayar dua puluh ribu untuk operator warnet di kampong”, begitu alasannya. Tentu saya terperangah atas permintaannya itu.
Di awal ‘2000-an ketika masih tinggal di Larantuka, sebuah kota kabupaten kecil di provinsi NTT, internet memang sesuatu yang asing bagi saya. Keberadaannya di Indonesia samar-samar sudah kami dengar kala itu, namun wujudnya masih teka-teki. Bayangkan, betapa tertinggalnya! Di 1997 atau 1996 saja, surat kabar Kompas dan Jakarta Post sudah menurunkan laporan perihalnya. Butuh hampir satu dekade untuk internet bisa hadir di kota kecil di wilayah timur Indonesia. Kembali pada permintaan seorang kawan di atas, membuat Facebook bagi kita di kota-kota besar tentu hal remeh; seremeh menempelkan Flazz Card BCA di pintu masuk halte Trans Jakarta. Teatapi, memang begitulah kenyataan jurang pengetahuan kita. Anda tentu tak perlu berpikir tujuh kali untuk menerka: ketika saya membuatkan Facebook itu, saya mulai dengan membuatkannya email pribadi dengan serentetan nasihat soal pentingnya kerahasiaan dan mengingat pasword-nya. Apa daya, pasword-nya pun dipercayakan pada saya untuk memikirkannya. Terdengar konyol tentu saja.
Jangankan internet dan segala perangkat pendukungnya, hal yang sama juga terjadi pada handphone. Saya pribadi baru menggunakan telepon genggam pada pertengahan 2003 ketika pindah ke Jakarta untuk berkuliah. Masa pacaran waktu SMA saya jauh dari budaya mengirimkan layanan pesan pendek. Apalagi bernyanyi-nyanyi via pesan suara di whatsapp atau line. Kalau tak salah ingat, kabar dari kampung perihal mulai bisa digunakannya handphone di Larantuka baru terdengar dua atau tiga tahun setelahnya. Tentu banyak cerita yang menyertainya, menjadi bumbu masuknya benda satu ini di sana.
Larantuka adalah sebuah kota kecil. Jalan utama hanya satu, terbentang dari timur ke barat yang dengan kecepatan sedang-sedang saja pun anda hanya perlu 45 menit kurang untuk menjelajahinya dari ujung ke ujung. Angkutan umum hanya ada dua jurusan; jurusan barat hingga pusat kota dan jurusan pusat kota hingga timur kota. Secara geografis, kota ini dekat dengan laut sehingga banyak penduduknya menjadi nelayan. Mencari ikan biasa dilakukan di malam hari. Dahulu, jika sampan yang satu kehabisan umpan, biasanya ia akan berteriak kepada teman di sampan sebelahnya untuk meminta umpan. Kini, dengan adanya handphone, berbagi umpan di kala memancing, terjadi di dalam diam; cukup ‘meng-ha-pe’ kawannya.
Oh ya, sebelum smartphone nge-trend, sebutan ‘ha-pe’ di Larantuka tidak hanya dipakai sebagai sekadar penanda handphone, tetapi juga untuk menandai segala aktivitas yang bisa dilakukan handphone. Jadi, mengirimkan sms dan menelepon telepon genggem disebut dengan ‘meng-ha-pe’. Penggunaan kata ‘meng-ha-pe’ ini mulai berubah ketika smartphone dan blackberry mulai masuk. Semakin banyak aplikasi dalam ‘handphone’ yang tak bisa lagi mereka wakilkan hanya dengan kata ‘meng-ha-pe’. Ketika penggunaan handphone mulai marak di sana, seseorang yang naik angkot dan handphone-nya berdering, makan seisi angkot mencibirnya, tentu dengan bisik-bisik. Entah karena apa. Ketika handphone buatan Cina mulai memasuki pasar, orang di sana melabeli handphone merk Cina dengan sebutan ‘fotokopian Nokia’. Tentu mendengar cerita-cerita di awal, saya yang kala itu sudah menjadi warga Jakarta, secara selera mau pun Kartu Tanda Penduduk, tertawa geli.
Internet Masuk Desa
Internet, pada dua atau tiga tahun terakhir ini merangsek masuk hingga wilayah-wilayah Indonesia Timur. Di awal 2000-an, internet, barangkali juga komputer, masih sesuatu yang asing di wilayah-wilayah timur Indonesia, khususnya di kota-kota kabupaten. Sedikit berbeda barangkali untuk daerah-daerah di Sulawesi. Tentu bukan tak ada sama sekali. Sejak akhir 1990-an internet sepertinya sudah bisa diakses melalui Telkomnet Instan dan Fixed Line Telkomsel di daerah-daerah. Namun, harga yang terlampau mahal—apalagi memang telepon pun bukan sesuatu yang sangat ‘merakyat’ juga—membuatnya bukan barang komoditi untuk semua orang. Secara umum, adanya Telkom Speedy di NTT-lah yang membuat mulai munculnya warnet-warnet di tahun 2009.
Tahun 2010 bisa dikatakan sebagai waktu meluasnya penggunaan internet di NTT. Melalui Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation dari Kominfo, pada September 2010, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) tersebar di 223 Kecamatan di NTT. Bukan hanya membangun semacam warnet di kota-kota kecamatan, program ini juga menghadirkan mobil internet, bahkan rencananya kala itu juga pengadaan kapal internet. Tentu banyak yang menaruh harapan atas kemajuan ini. Misalnya, semakin terbukanya peluang masyarakat umum untuk mendapatkan akses informasi dan juga keuntungan-keuntungan lainnya via teknologi internet. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah benarkah “Internet Masuk Desa” ini membawa keuntungan dan manfaat yang signifikan untuk masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia?
Menjawab pertanyaan tersebut tentu membutuhkan penelitian dan pengamatan yang lebih terperinci. Tergantung pula dari sudut mana kita melihat. Setidaknya sejauh ini peluang-peluang bagi masyarakat di daerah-daerah pelosok semakin terbuka lebar. Hampir bersamaan dengan meluasnya penggunaan internet tersebut, di NTT, geliat sastra terdengar hingga ke Jakarta. Para pegiat sastra di sana, khususnya di kota Kupang, lancar berbagi informasi dengan sesamanya di kota-kota lain di Indonesia, khususnya di Yogyakarta dan Jakarta. Keberadaan internet juga memudahkan para penulis sastra di sana mengirimkan karya mereka ke media-media yang berada di luar wilayah mereka. Selain itu, tentu memudahkan pula mereka terlibat dalam diskusi-diskusi dan wacana-wacana sastra mutakhir.
Hal ini jauh berbeda dengan generasi sastrawan NTT sebelumnya. Saya pernah bertemu dengan seorang penulis sastra dari NTT yang di era ‘70-an dan ‘80-an kerap mengisi laman-laman sastra di koran-koran Yogyakarta, maupun Jakarta. Namun, namanya pudar di era ‘90-an hingga sekarang. Setelah diusut, keaktifannya itu terjadi ketika ia masih menjadi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Mengirimkan tulisan ke koran Yogyakarta cukup dengan mendatangi kantor redaksinya, sedangkan mengirim tulisan ke media Jakarta hanya butuh waktu beberapa hari saja. Setelah selesai studi, ia memutuskan kembali ke NTT dan ia tak lagi mengirimkan karyanya ke media-media di kedua kota tersebut. Alasannya sederhana. Hampir semua media terbitan Jakarta dan Yogyakarta kala itu tidak bisa didapatkan di kota kabupaten di NTT. Di samping itu, pengiriman karya melalui pos memakan waktu yang cukup lama.
Menurut Joseph Letor, koordinator PLIK NTT yang mempunyai akses ke 223 PLIK se-NTT, peringkat penggunaan internet di NTT bisa disebutkan lima hal. Yaitu, untuk jejaring sosial (facebook), mencari tugas sekolah, mencari informasi pertanian dan perikanan, (seperti harga mente, pupuk, dll.), belajar online khususnya bagi mahasiswa Universitas Terbuka, dan penggunaan e-mail yang sangat kecil jumlahnya. Dari lima penggunaan ini terlihat bahwa memang ada pemanfaatan yang cukup positif bagi masyarakat di desa. Pencarian informasi pertanian dan perikanan misalnya. Pengakuan Franco Nalele, seorang pengelola warnet bantuan PLIK di salah satu kelurahan di kota Larantuka, dalam seminggu pengunjung warnetnya berkisar antara 30-40 orang. Kebanyakan dari pengunjung itu menggunakan warnet untuk mengerjakan tugas, khusus untuk para pelajar. Penggunaan warnet untuk media sosial tidaklah banyak. Hal ini dimungkinkan karena kebanyakan pengguna media sosial bisa melalui smartphone. Patut dicatat, internet pribadi di rumah cukup jarang ditemukan di sana.
Meme Rasa Daerah
Di tengah penggunaan yang demikian, sedikit-sedikit media gambar digital pun perlahan-lahan muncul di sana seiring penggunaan internet. Memang tidak banyak. Sejauh pengamatan, pengguna media sosial di Larantuka yang juga asyik ber-meme ria hanya dua orang. Itu pun lantaran mereka sehari-harinya dekat dengan internet dan komputer alias bekerja di warnet. Sedangkan ‘tradisi’ produksi meme mungkin lebih hidup di Kupang yang adalah kota provinsi NTT. Dari wawancara dengan Franco Nalele, salah satu pengguna facebook di Larantuka yang aktif membuat meme, ia pun terinspirasi dari aktivitas serupa yang ada di Kupang, terkhusus dari account facebook bernama Kalapa Mati.
Kalapa Mati, sejauh pantauan saya mulai aktif membuat meme sejak lima atau tujuh tahun yang lalu. Meme-meme lokal ini menimbulkan fenomena memindahkan ekspresi-ekspresi verbal ‘kedaerahan’ menjadi media gambar digital dengan alat penyebarnya; media sosial. Meme-meme banyak memanfaatkan ungkapan-ungkapan lisan kedaerahan. Saya belum terlalu jelas apa yang memicu fenomena ini. Barangkali memang sekadar respon dan produksi lokal atas apa yang ada dan mereka konsumsi dari pusat. Berbeda dengan cerita tentang para sastrawan di atas, yang memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dengan sastrawan di wilayah lain. Pada fenomena meme, mungkin tak ada niat untuk berkomunikasi atau membangun jejaring dengan siapa pun, atau tujuan tertentu lainnya. Sejauh menurut saya, tujuannya sekadar bersenang-senang mengisi waktu luang. Apa yang mereka hasilkan pun tak berpretensi. Namun, memang agak sulit untuk dipahami oleh orang lain atau komunitas lain di luar komunitas kedaerahan mereka. Simak misalnya dua meme yang dibuat oleh salah satu akun Facebook pemuda dari Flores Timur berikut ini.

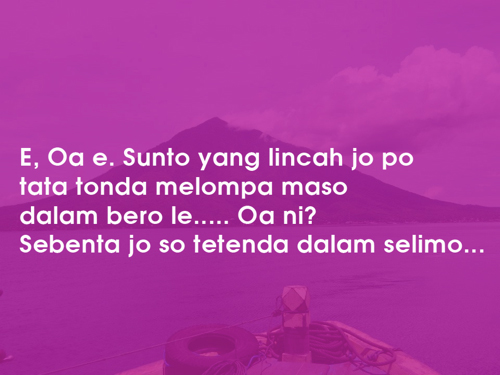
Kalimat-kalimat yang ada pada kedua meme tersebut tampak sulit untuk dipahami oleh orang yang berada di luar komunitas daerah tersebut. Jika diterjemahkan pun, hanya meme pertamalah yang bisa dipahami sepenuhnya. “Oa e… Foto bua gaya lee mireng macam orang tido banta tesala ni…? Supaya apa…??? Hahaerrooo.” Terjemahan bahasanya kira-kira demikian, “Hai Nona, berfoto dengan maksud untuk bergaya kok seperti orang yang lehernya sakit lantaran salah kepala ketika tidur? Untuk apa? Hahahahahaha.” Sementara untuk meme yang kedua, “E, Oa e. Sunto yang lincah jo tata tonda melompa maso dalam bero le… Oa ni? Sebenta jo so tetenda dalam selimo….” Kira-kira artinya, “Nona. Cumi-cumi yang lincah berenangnya pun bisa saya arahkan untuk melompat masuk ke dalam sampan. Anda? Hanya butuh waktu sebentar untuk membuatmu berada di dalam selimut.”
Untuk meme yang kedua ini, kita perlu memahami simbol-simbol serta praktek nelayan di wilayah tersebut. Betapa sulit untuk berhasil menangkap seekor cumi-cumi dibandingkan dengan jenis hewan laut lainnya. Kita juga perlu memahami seperti apa kelincahan cumi-cumi ketika berenang di dalam air laut. Entah disengaja atau tidak, meme pertama hanya berupa kata-kata, sedangkan meme kedua ada gambar ujung depan perahu yang berlayar menuju daratan. Gambar ini pada hemat saya semakin memperkuat aroma lokalitasnya, meski pun masih ada unsur eksotisme yang barangkali disengaja atau tidak
Selain meme-meme ‘becandaan’ seperti di atas, mereka juga kerap membuat meme berbauh ‘rohani’ dengan kekhasan yang mirip dengan budaya rohani setempat. Larantuka dikenal juga dengan tradisi Katoliknya yang kental serta devosi pada Bunda Maria. Bahkan di kota itu ketika Paskah Katolik tiba, ada prosesi yang merupakan perpaduan antara kekatolikan dan kebudayaan lokal[1]. Maka tidak heran, menjelang Paskah muncul pula meme seperti ini:

Kelokalan pun tampak pada meme-meme yang ada di account facebook Kalapa Mati.


Untuk meme pertama—seingat saya, muncul bersamaan dengan issue kenaikan harga BBM—dengan kalimat, “puji Tuhan, Laporan harga BBM (Belis Buat Maitua) masih stabil”. Kita melihat bagaimana BBM atau Bahan Bakar Minyak ‘diplesetin’ menjadi Belis Buat Maitua yang sangat beraroma kelokalan. Dalam adat pernikahan di wilayah NTT, mengharuskan keluarga lelaki menyerahkan belis kepada keluarga perempuan—seringnya harga belis itu mahal tak terkira. Dari kalimat di meme tersebut, tampaklah ungkapan kebahagiaan karena harga belis tidak naik. Jika harga belis naik, maka urusan pernikahan bisa jadi lebih sulit.
Jika kelokalan pada meme pertama adalah adat istiadat maka kelokalan pada meme kedua terletak pada komoditas dagang yang ada di Kupang. Kalimat dalam meme tersebut demikian, “NABAS adalah singkatan dari Nasi Babi Sate”. NABAS merupakan jenis makanan yang sangat mudah didapatkan di warung kaki lima di Kupang. Menunya, biasanya terdiri atas nasi kuning dengan daging babi yang dimasak dengan cara tertentu ditambah sate daging babi. NABAS mungkin sangat sulit didapatkan di wilayah lain di Indonesia. Hal yang menarik, NABAS pada meme ini disandingkan dengan KFC yang lebih mengglobal keberadaannya.
Selain kelokalan yang asli dan khas, ada juga meme yang berusaha mengubah meme-meme ‘Jakarta’ ke dalam bahasa lokal. Misalnya meme berikut:

Foto lelaki negro di atas, kerap dijadikan meme dengan kalimat “Di situ kadang saya merasa sedih”, sebuah frase yang popular lantaran diucapkan seorang Polwan di salah satu televisi swasta—sayang, hingga tulisan ini selesai, saya tak berhasil menemukan meme yang dimaksud. Meme yang ditampilkan ini pada hemat saya adalah usaha untuk memparafrasekan “di situ kadang saya merasa sedih” dalam ungkapan lokal Larantuka, dua frase ini punya nilai pemaknaan yang mirip.
Dua ilustrasi di atas, saya kira mewakili dua ekstrem penggunaan internet di daerah-daerah di luar pulau-pulau besar wilayah barat Indonesia. Jika kita membuat daftarnya, tentu banyak lagi yang barangkali hampir sama di setiap wilayah. Belum lagi jika kita hendak melihat bagaimana bahasa daerah terkadang sulit menemukan padanan huruf-huruf yang mewakili bunyi pelafalannya, khususnya untuk bahasa daerah tanpa tradisi aksara, seperti dalam aksara romawi yang digunakan oleh komputer di Indonesia pada umumnya.
Menjamurnya penggunaan internet di Indonesia secara keseluruhan memicu juga praktek meme. Pada Pemilu Presiden tahun 2014, meme-meme membanjir di tengah media kampanye lainnya. Seiring juga masuknya internet di daerah-daerah lain di Indonesia, muncul pula praktek meme di sana yang tentunya mendapat sentuhan lokal.
* * *
Demikianlah. Untuk daerah yang jauh dari pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan, seumpama lagu lama, kemajuan teknologi tidak serta merta menyapa mereka. Banyak pengalaman mencatat, salah ‘duanya’ adalah telepon dan internet, butuh waktu cukup lama untuk masyarakat daerah bisa merasakan kemajuan teknologi; sebuah kemajuan yang secara langsung atau pun tak langsung diakomodir oleh mereka. Desa bukan hadir tanpa arti; ia hadir selalu sebagai pendukung atas kota-kota maju yang menjadi pusat berkembangnya kebudayaan, teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
Ketika teknologi itu pada akhirnya menyapa mereka terkadang mereka memang siap, terkadang juga tidak. Namun yang terpenting adalah kemampuan mereka untuk cepat berbenah diri dan menyesuaikan diri dengan derap dunia yang ada di luar mereka. Memang tidak semua memiliki kemampuan itu. Praktek meme yang sedikit banyak digambarkan di dalam tulisan ini, saya kira adalah bukti awalnya. Sedangkan ketaksiapan masyarakat pada teknologi baru, sedikt banyak muncul pula dalam anekdot-anekdot serta tingkah laku yang aneh dalam penggunaan alat-alat teknologi baru itu. Tingkah laku dalam kehidupan mereka, barangkali tidak drastis, tetapi turut berubah seiring masuknya teknologi-teknologi baru tersebut. Namun bersamaan dengan itu, “namanya juga program pemerintah”, terdengar kabar bahwa jaringan internet beberapa PLIK di kecamatan-kecamatan akan dicabut.
Menutup tulisan ini, saya hendak menceritakan ulang sebuah kisah dari Papua tentang seorang lelaki yang membeli handphone. Alkisah, seorang Pace dari kampung datang ke toko elektronik di Sorong, salah satu kotamadya di Provinsi Papua Barat, untuk membeli handphone. Selain handphone, ia pun membeli sim card telkomsel. Setelah itu, Pace tersebut pulang ke kampungnya. Beberapa minggu kemudian ia datang lagi ke toko elektronik tersebut sembari marah-marah lantaran handphone-nya tak bisa digunakan. Sang penjaga toko, katakanlah pendatang dari Sulawesi, bertanya tentang di mana tempat tinggal Pace tersebut. Pace pun menyebutkan nama kampungnya. Si Penjaga Toko dengan tersenyum sabar menjelaskan kepada Pace bahwa di kampung itu memang sinyal belum masuk. Dengan masih menyimpan emosi, Si Pace menjawab, “Kalau begitu, saya beli sinyal langsung dua buah!”
[1] Untuk contoh, silahkan cek “Tradisi Paskah di Larantuka”, http://nasional.kompas.com/read/2011/04/21/09355774/Tradisi.Paskah.di.Larantuka. Diakses pada 28 Mei 2015.
*Catatan: Tulisan ini dibuat untuk katalog OK.Video 2015: Orde Baru. Diunggah juga di website OK.Video.




