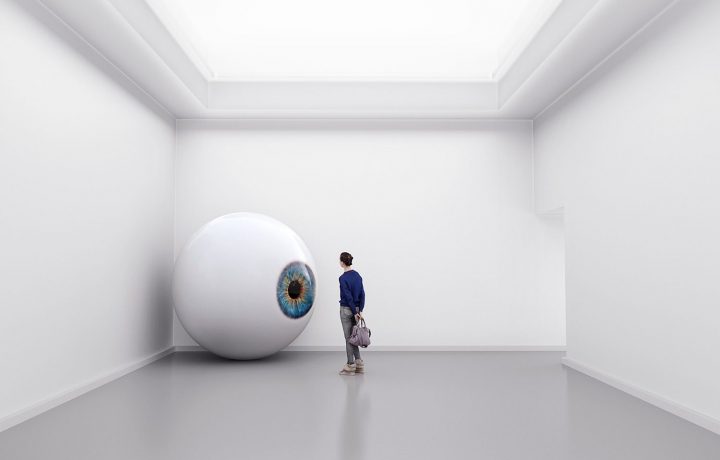Driyarkara dikenal sebagai seorang pemikir yang mana namanya dibadadikan sebagai nama sebuah sekolah tinggi filsafat yang ada di Jakarta. N. Driyarkara sendiri—sebagaimana banyak pemikir dan tokoh bangsa Indonesia yang tetap dikenang sampai saat ini—hidup dan aktif pada sebuah masa yang penting (1950-an hingga 1970-an) yakni masa ketika Bangsa Indonesia sedang berusaha memperkuat dan memperkokoh nasionnya yang dengan susah payah sudah direbut dari penjajah pada masa Revolusi Fisik beberapa tahun sebelumnya. Sebagai orang yang hidup pada zaman yang demikian, Driyarkara melalui tulisan-tulisannya menunjukan pada kita bahwa ia memang anak zaman itu, ia memang terlibat dengan roh zaman itu.
Untuk itu, dalam tulisan ini saya akan memaparkan pemikiran Driyarkara tentang revolusi—yang merupakan kata yang sangat familiar untuk masyarakat Indonesia masa itu dan bisa dikatakan sebagai semangat zaman itu, terlepas dari kelemahan dan kekurangannya—yang termuat dalam tulisan-tulisan Driyarkara. Tulisan-tulisan Driyarkara yang menjadi rujukan saya adalah “Romantik Revolusi”, “Dialektik Revolusi”, “Revolusi: Romantik, Dinamika, Dialektika”, dan “Demonstrasi, Mogok, Demokrasi”. Keempat tulisan itu saya ambil dari buku Karya Lengkap Driyarkara.[1] Selain itu, saya juga menggunakan sebuah tulisan Driyarkara yang tidak dicantumkan dalam karya lengkap itu yakni tulisan bertajuk Vivere Pericoloso[2]. Dalam tulisan ini pertama saya akan coba memaparkan keadaan Indonesia pada 1950-1960an, waktu-waktu ketika tulisan Driyarkara yang menjadi rujukan utama tulisan ini ditulis dan atau diterbitkan. Kedua, saya akan masuk pada beberapa pemikiran Driyarkara yang saya sarikan dari tulisan-tulisan Driyarkara yang saya rujuk. Bagian kedua ini akan kita bagi dalam beberapa pokok pembahasan. Dan ketiga, saya akan meringkaskan apa yang dipikirkan Driyarkara tentang revolusi di Indonesia itu.
Indonesia 1950-1960-an dan Revolusi
Membicarakan Indonesia dan juga dunia umumnya pada era 1950-an hingga 1960-an, kita tentu tidak bisa menutup mata pada keadaan dunia masa itu secara keseluruhan yakni Perang Dingin. Indonesia dalam perkembangan waktu itu tidak memilih untuk berada pada salah satu pihak yang berseteru yakni Paktawarsawa dan atau NATO. Indonesia bersama beberapa Negara dunia ketiga lainnya justru membentuk apa yang disebut sebagai Gerakan Non Blok. Di dalam negeri sendiri pertarungan secara politik antara ideologi-ideologi yang berbeda pun terjadi. Maka dari masa itu pula kita mengenal adanya istilah Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunisme) yang oleh beberapa sejarahwan dianggap sebagai sebuah upaya Soekarno untuk menyatukan keberagaman tendensi di ranah politik kala itu di Indonesia.

Namun, perbuatan Soekarno seperti ini pun bukannya tidak punya risiko. Dengan melihat kenyataan bahwa sistem parlementer tidak berjalan dengan semestinya—adanya tarik ulur dari beragam kepentingan partai yang ada di parlemen—Soekarno lantas membuat apa yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin. Kekecewaan Soekarno pada sistem partai itu terlihat dalam pidatonya pada 1956 di hadapan pemuda:
Ada penyakit yang kadang-kadang bahkan lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan! Engkau bertanya, penyakit apakah itu? Itulah penyakit kepartaian, saudara-saudara! Ya, aku akan berterus-terang; itu penyakit kepartaian. Pada bulan November 1945—baiklah kita berterus terang—kita telah membuat kesalahan besar. Kita menganjur-anjurkan pembentukan partai-partai, partai-partai, partai-partai. Itulah salah satu kesalahan pada bulan November 1945. Sekarang kita menanggung akibat-akibatnya. Lihatlah keadaan kita! Selain penyakit kesukuan dan kesetiaan kedaerahan, kita terkena penyakit kepartaian yang sayang sekali, sayang sekali, menyebabkan kita selalu cakar-cakaran satu sama lain… Sekarang marilah kita bersama-sama mengubur semua partai.[3]
Kita tahu, selain masalah tarik ulur kepentingan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, Indonesia di tahun-tahun itu pun dihantui oleh separasi kedaerahan.[4] Demokrasi terpimpin sendiri akirnya muncul Dekrit 5 Juli 1959 yang menginstruksikan untuk kembali ke UUD 1945 yang memberi angin segar untuk diterapkannya Demokrasi Terpimpin.
Selain problem dalam bentuk demokrasi—demokrasi parlementer atau demokrasi terpimpin—bagi masyarakat Indonesia kebanyakan saat itu revolusi menjadi kata penting bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu kalimat penting Soekarno yang dikumandangkan saat itu adalah “revolusi belum selesai”. Revolusi di sini menjadi kata yang biasa dan menjadi jargon di dalam banyak kehidupan masyarakat.[5] Kata revolusi inilah yang direfleksikan secara mendalam oleh Driyarkara di dalam tulisan-tulisannya yang menjadi pokok utama tulisan saya ini. Tentu di saat itu sarjana filsafat di Indonesia belum banyak dan bisa dikatakan langka. Driyarkara adalah salah satu dari yang langka itu. Itu berarti tentu secara akademis memang sangat sedikit orang yang mengenyam pendidikan filsafat. Namun wacana filsafat saya kira bukanlah sesuatu yang asing benar di Indonesia kala itu. Salah satu contohnya, penulis seperti Jean-Paul Sartre pun tulisannya dipublikasikan oleh redaksi koran.[6] Untuk lebih memperdalam apa yang dipandang oleh Driyarkara dengan revolusi, pada bagian berikut kita akan mengkajinya.
Revolusi dalam Pandangan Driyarkara[7]
Revolusi sebagai Sesuatu yang Penting
Driyarkara mengatakan bahwa revolusi adalah sebuah perbuatan mendalam yang menjebol orde lama menuju orde baru. Tentu saja orde lama dan orde baru yang dimaksudkan oleh Driyarkara di sini bukan dalam pengertian massa kepemimpinan di Indonesia. Kita juga perlu memperhatikan kata “perbuatan” di atas. Dengan mengetengahkan kata “perbuatan”, revolusi dalam pandangan Driyarkara bisa dikatakan merujuk pada “kerja tertentu” atau “aksi” tertentu. Perhatikan pula apa yang dikatakannya selanjutnya mengenai rasa romantik revolusi sebagai sebuah rasa yang hanya mungkin dihayati oleh orang yang tekun bekerja tanpa bicara daripada orang yang banyak bicara tanpa berbuat sesuatu[8].
Romantik adalah sebuah perasaan yang mendalam, sebuah perasaan yang mendalam. Kenapa ia menjadi sebuah perasaan mendalam? Karena romantik itu adalah sebuah perasaan yang muncul hanya ketika manusia benar-benar berdialektika antara kerohaniannya dengan kejasmaniannya. Demikian Driyarkara berujar, “romantik adalah suatu situasi manusia jasmani-rohani; romantik dalam artinya yang sesungguhnya adalah sebuah perasaan manusia yang menunjukan kerohaniannya yang “berdialektika” dengan kejasmaniannya”[9]. Maka romantika bisa muncul pada manusia ketika manusia tersebut benar-benar melakukan sesuatu dengan mendalam.
Maka, sesungguhnya revolusi menurut Driyarkara adalah sebuah perbuatan yang mendalam yakni sebuah perbuatan yang mengharuskan manusia mendialektikakan unsur rohaninya dengan unsur jasmaninya. Itulah sebabnya Driyarkara menekankan unsur romantik dalam revolusi. Driyarkara menunjukan betapa revolusi adalah sebuah perbuatan serius yang sungguh-sungguh dijalankan manusia yang berjasmani-berohani yang pada pokok utama manusia itu digerakan oleh rohaninya. Itu berarti jika di dalam sebuah revolusi atau di dalam jiwa seorang revolusioner tak ada unsur atau perasaan romantik terhadap revolusi itu sendiri, dia sesungguhnya belum benar-benar menjalankan revolusi.
Revolusi adalah Dialektika
Pada pembahasannya mengenai dialektika revolusi, Driyarkara menggunakan unsur kebudayaan Jawa untuk menjelaskan dialektika itu yakni ia menggunakan dialektika wahya-jatmika. Menurut Driyarkara, manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan unsur rohani; tak ada manusia yang hanya terdiri dari satu unsur saja. Sehingga, di dalam diri manusia itu sendiri sudah ada dialektika yakni dialektika antara unsur jasmani dan unsur rohaninya atau yang disebutnya dengan dialektika Wahya-Jatmika.
Karena pada dirinya sendiri sudah ada dialektika, maka di dalama hidup bermasyarakat pun tentu akan ada dialektia. Kenapa demikian? Karena menurut Driyarkara, masyarakat itu menjadi mungkin ada karena adanya individu-individu yang menjadi anggota dari masyarakat itu sendiri. Salah satu dialektika dalam kehidupan bermasyarakat adalah revolusi tersebut. Menurut Driyarkara pula, dialektika itu tidak pernah selesai. Dialektika bagi Driyarkara akan selalu ada karena dialektika itu inheren dalam hidup manusia sendiri.
Di sini bisa kita simpulkan bahwa dialektika yang coba dipahami Driyarakara beda dengan dialektika a la Hegel. Bagi Hegel, dialektika adalah perjalanan roh untuk mencapai Roh Absolut. Di dalam dialektika Hegel pula manusia hanyalah sebatas ekspresi dari Roh tersebut. Namun Driyarkara dengan menekankan bahwa di dalam diri manusia itu sendiri pun ada dialektika karena manusia itu pada dasarnya terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang senantiasa saling berdialektika, maka di sini Driyarkara menempatkan posisi manusia cukup penting dalam dialektika, sesuatu yang tak ditemui dalam dialektika Hegel. Perbedaan yang kedua dengan dialektika Hegel adalah bahwa Driyarkara tidak melihat adanya akir dari dialektika—jika di dalam dialektika Hegel akir itu adalah pemenuhan diri Roh Absolut. Dialektika senantiasa ada karena dialektika itu ada dalam diri manusia. Artinya, dialektika itu akan berhenti hanya jika tak ada manusia lagi. Otomatis jika tak ada manusia lagi, tak ada lagi pikiran yang bisa mencerna realitas dan bisa memaknai realitas itu sendiri. Realitas materil mungkin akan tetap ada tetapi dia tak berarti untuk manusia karena manusia sudah tak ada.

Selain akir dialektika Hegel, rupa-rupanya Driyarkara juga menyerang akir sejarah a la dialektika marxisme fulgar yang mempercayai akir sejarah sebagai kemenangan kelas proletar yang mana mengakibatkan emansipasi di segala penjuru. Demikian Driyarkara, “…nonsense belakalah jika orang mengira bahwa masyarakat manusia akan mencapai status terakhir dengan kenikmatan sosial ekonomis yang tak terganggu, di mana semua bekerja untuk semua dengan semua kekuatannya dan mendapat bagian kenikmatan sesuai dengan kebutuhannya”[10].
Maka, dialektika di dalam masyarakat dengan demikian akan selalu ada dan tak akan pernah mencapai titik akir. Salah satu dialektika di dalam masyarakat adalah revolusi maka revolusi itu sendiri pun tak akan pernah selesai karena akan selalu senantiasa ada “orde baru” lain yang mencoba menembus dinding-dinding kokoh “orde lama” apa pun ketika “orde” tersebut semakin terlihat usang dan tak mewadahi kebutuhan manusia lagi.
Revolusi Pancasila
Sebelum berlanjut, kita harus mengingat beberapa pokok penting pemikiran Driyarkara tentang revolusi di atas. Pertama, revolusi adalah bentuk dialektika di dalam masyarakat. Dialektika dimungkinkan karena yang menghidupi hidup adalah manusia dan di dalam diri manusia itu sendiri secara inheren ada dialektika. Sedangkan di dalam revolusi yang adalah dialektika itu ada unsur romantik yang menunjukan bahwa revolusi adalah sebuah perbuatan yang sungguh-sungguh mendalam, artinya sebuah perbuatan yang sungguh-sungguh melibatkan jiwa manusia karena di antara rohani dan jasmani tadi, pokok utamanya menurut Driyarkara adalah jasmani manusia.
Revolusi yang demikian itu didorong oleh apa yang disebut dengan dinamika revolusi. Dinamika revolusi muncul dari jiwa rohani manusia. Karena revolusi yang dibicarakan oleh Driyarkara adalah revolusi di Indonesia maka menurut Driyarkara kejiwaan Indonesia yang sungguh-sungguh menunjukan dialektika antara jasmani dan rohani itu adalah jiwa yang harus benar-benar berdasarkan Pancasila. Pancasila kita tahu adalah lambang atau azas hidup Indonesia. Bagi Driyarkara, jiwa dialektika jasmani rohani manusia Indonesia itu diekspresikan dengan baik dalam Pancasila itu sendiri.
Driyarkara menunjukan bagaimana hubungan antara dinamika dan romantisme revolusi. Menurutnya, jika dinamika yang memunculkan revolusi maka romantisme revolusilah yang akan terus memberi bahan bakar pada dinamika itu. Namun di dalam revolusi itu sendiri terdapat sesuatu yang justru bisa berbalik menjadi kontra revolusi. Driyarkara menjelaskan bahwa revolusi pertama-tama adalah kontra dialektika dalam pengertian bahwa revolusi merupakan dialektika yang melawan dialektik yang sudah membalik menjadi lawan dari dialektik yang sebenarnya. Oleh karena itu bagi Driyarkara di dalam dinamika, dialektika, dan romantika—ketiga-tiganya adalah unsur revolusi—terdapat bahaya yakni di dalamnya selalu ada unsur-unsur yang kontradiktif dan menghancurkan.
Penutup: Revolusi via Vivere Pericoloso
Setelah membahas beberapa unsur dalam revolusi yang diungkapkan Driyarkara, berikut kita akan memberikan beberapa ringkasan dan catatan.
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa revolusi itu merupakan dialektika dan dialektika itu selalu akan terjadi. Selain itu, secara eksplisit kita menemukan bahwa karena revolusi ada unsur romantiknya yang mana unsur romantik itu dimungkinkan oleh mereka yang benar-benar ‘mendalami’ revolusinya maka ada kontra revolusi yang mungkin mucul dari mereka yang tidak mempunyai unsur revolusi yang mendalam. Mereka inilah yang akan menjadi unsur dialektika yang keluar dari dialektika sebenarnya. Mereka inilah yang harus menjadi lawan dari revolusi yang sebenarnya. Dengan memasukan unsur ‘kelemahan’ dialektika dalam dialektika itu sendiri, sesungguhnya dialektika terus berjalan menuju keparipurnaan. Demikian juga revolusi. Tetapi karena dialektika tidak ada keparipurnaannya menurut Driyarkara maka kerja keraslah yang dibutuhkan untuk terus berada dalam jalur revolusi sebenarnya yakni jalur revolusi yang melawan kontra-kontranya.
Revolusi yang tak pernah lelah melawan kontra-kontranya demi ke luar dari “orde lama” menuju “orde baru” ini butuh kerja keras. Kerja keras yang dimaksud adalah keberanian bertindak walau pun tanpa kepastian atau apa yang oleh Driyarkara disebut sebagai “vivere pericoloso”[11]. Revolusi Indonesia dengan demikian membutuhkan manusia-manusia yang “vivere pericoloso” yakni mereka yang mau terus bekerja keras melawan kontra-kontra revolusi tersebut dan mereka yang juga berlandaskan jiwa Pancasila.
[1] A. Sudiarja, SJ, G. Budi Subanar, SJ, St. Sunardi, dan T. Sarkim (peny.), Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2006, hlm. 627-650.
[2] Prof. Dr. Drijarkoro, SJ, “Vivere Pericoloso”, Kompas, 10 September 1965.
[3] Sebagaimana dikutip oleh In Nugroho Budisantoso, “Hatta Mundur Karena Kecewa?”, dlm Rikard Bagun (ed.), Seratus Tahun Bung Hatta, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 2002, hlm. 350.
[4] Onghokham, Soekarno, Orang Kiri, Revolusi dan G30S 1965, (Depok: Komunitas Bambu), 2009, hlm. 27.
[5] Pada kesempatan presentasi di kelas Filsafat Driyarkara beberapa waktu lalu, saya menduga bahwa kata revolusi hanya muncul sebatas jargon tetapi untuk membenarkan pernyataan saya itu tentu membutuhkan penelitian tersebdiri. Untuk itu maka pada kesempatan ini pendirian saya adalah bahwa mungkin di kalangan rakyat jelata pemahaman seputar revolusi tidak terlalu memadai. Namun di kalangan intelektual kala itu tentu kata revolusi ini terpahamkan sesuai dengan latar belakang ilmu mereka masing-masing.
[6] Yang saya maksud adalah Koran Harian Rakjat. Pada 12 November 1955, redaksi harian tersebut menerbitkan tulisan Jean-Paul Satre bertajuk “Kebenaran di Tiongkok adalah: Haridepan”, Harian Rakjat, 12 November 1955.
[7] Hampir semua pemaparan bagian ini bersumber dari A. Sudiarja, SJ, G. Budi Subanar, SJ, St. Sunardi, dan T. Sarkim (peny.), Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2006, hlm. 627-650.
[8] A. Sudiarja, SJ, G. Budi Subanar, SJ, St. Sunardi, dan T. Sarkim (peny.), Karya Lengkap Driyarkara:…, hlm. 630.
[9] A. Sudiarja, SJ, G. Budi Subanar, SJ, St. Sunardi, dan T. Sarkim (peny.), Karya Lengkap Driyarkara:…, hlm. 635.
[10] A. Sudiarja, SJ, G. Budi Subanar, SJ, St. Sunardi, dan T. Sarkim (peny.), Karya Lengkap Driyarkara:…, hlm. 637.
[11] Prof. Dr. Drijarkoro, SJ, “Vivere Pericoloso”, Kompas, 10 September 1965. Vivere Pericoloso pernah dipakai Soekarno sebagai semboyan pula untuk membicarakan revolusi. Istilah ini diambil Soekarno dari Musollini. Lihat Onghokam, Soekarno, Orang Kiri, Revolusi dan G30S 1965…, hlm. 55. Apakah Driyarkara terinspirasi juga dari semboyan yang dipakai Soekarno ini dalam artikel yang dimuat di Kompas di atas ataukah Driyarkara mengembangkannya lebih lanjut? Hal ini mungkin butuh sebuah penelitian lebih lanjut.
Catatan: Tulisan ini merupakan makalah akir pada kelas Filsafat Driyarkara di STF Driyarkara, semester genap 2011/2012.