Semacam pengantar: Dalam rangka menyambut diterbitkannya kembali Seikat Kisah tentang Yang Bohong, kumpulan cerpen saya, di sini saya menurunkan ulasan dari Bung Heru Joni Putra atas buku tersebut. Seikat Kisah tentang Yang Bohong awalnya diterbitkan oleh Penerbit Alpha Centauri (Yogyakarta) pada 2016. Pada awal 2020, buku ini diterbitkan ulang oleh Penerbit Buku Mojok (Yogyakarta).
Mengenai tulisan Bung Heru Joni Putra ini, awalnya merupakan tulisan pengantar untuk diskusi atas buku Seikat Kisah tentang Yang Bohong pada terbitan pertamanya, 2016 silam. Diskusi tersebut diadakan oleh Komunitas Agenda 18 bertempat di Yayasan Obor Indonesia, Jakarta pada Sabtu, 4 Maret 2017. Lantas, tulisan Heru ini dipublikasikan pertama kali di website Agenda 18.

Buku kumpulan cerita pendek karya Berto Tukan, Seikat Kisah tentang Yang Bohong (Alpha Centauri, 2016), membawa kita kembali kepada perbincangan mengenai aspek fiksionalitas dari karya sastra. Atau hubungan tarik-menarik antara “yang nyata” dan “yang fiktif” dalam karya sastra.
I
Seberapapun ada penekanan akan adanya aspek “kenyataan yang sebenarnya” dari suatu karya sastra, ia akan tetap hadir sebagai suatu fiksi. Karya-karya yang diberi label “berdasarkan kisah nyata” misalnya, memanglah tidak sepenuhnya nyata, dalam artian bahwa suatu kenyataan yang menjadi “asal-usul” kisah tersebut, dengan suatu dan lain cara, mengalami pengikisan di sana-sini, entah itu sekedar berupa penyesuasaian dengan tata bahasa, atau mengalami “penciptaan kembali” lewat piranti-piranti sastra. Bahkan, pada karya-karya yang mengukuhkan diri sebagai karya beraliran “realisme” sekalipun, sebagaimana kita tahu, “yang real” dari karya tersebut tak melulu terbatas soal apakah kisah di dalamnya “pernah terjadi” atau tidak sama sekali. Tetapi, salah satunya, lebih kepada apakah kisah tersebut mempunyai “struktur” yang sama dengan kenyataan, meskipun “tidak pernah terjadi” sekalipun.
“Kenyataan” memang tak bisa dihadirkan kembali sepenuhnya dalam karya sastra, akan tetapi tendensi “berdasarkan kisah nyata” dalam berbagai karya-cipta manusia, tak hanya sastra, film, tetapi juga acara televisi semacam reality show, tampak lebih diminati oleh masyarakat kita saat ini, bahkan pada taraf tertentu, yang “berdasarkan kisah nyata” lebih diposisikan sebagai “kenyataan” itu sendiri daripada “kenyataan yang sebenarnya”.

Artinya, “politik kisah nyata” bukanlah sesuatu yang asing dalam produk-produk budaya kita. Bahkan “politik kisah nyata” menjadi salah satu alat ampuh saat ini untuk menggiring opini publik, seperti dalam fenomena hoax. Artinya, suatu kisah bila suatu diberi label “kisah nyata”, maka tak jarang kisah tersebut lebih mendorong sebagian kita untuk mengetahuinya. Barangkali, di zaman teknologi informasi ini, masyarakat kita sedang berada dalam suatu kondisi di mana kebutuhan atas “realitas yang sebenarnya” semakin meningkat, tapi pada sisi tertentu tak awas terhadap segala yang mengatasnamakan “realitas yang sebenarnya”.
II
Buku cerita pendek Seikat Kisah tentang Yang Bohong, dengan pilihan judul tersebut, hadir ke hadapan kita dengan suatu kesadaran atas dirinya sendiri. Suatu kesadaran akan dimensi fiktif yang ada dalam dirinya atau yang menjadi sebab-musabab keberadaannya. Sebuah karya sastra yang dengan rendah hati mengakui bahwa ia bukanlah realitas yang sebenarnya atau tak terlalu berambisi untuk menggantikan kenyataan yang justru lebih kompleks, multi-konflik, bahkan tak sepenuhnya bisa diartikulasikan dengan piranti sastra.

Dengan adanya penekanan akan “yang bohong”, maka ia tidak sedang berusaha membohongi dan pembaca pun tak perlu merasa dibohongi sebagaimana cerita “berdasarkan kisah nyata” sering melakukan. Dengan tidak menekankan aspek “kisah nyata” dalam dirinya, ia mungkin tak ingin pembaca repot-repot mempersoalkan yang benar dan yang bohong. Ia sudah mewanti-wanti kita bahwa dirinya hanyalah sekumpulan “yang bohong” belaka, sehingga yang kita cari di dalamnya bisa saja lebih penting daripada sekedar mencari apa benar atau tidak kisah itu sendiri.
Kesadaran atas ke-fiktif-an dirinya sendiri juga dijadikan sebagai salah satu teknik bercerita. Dalam cerita berjudul Semper Reformanda, terdapat satu paragraf yang seakan berdiri sendiri dan sedikit berjarak dari jalan utama cerita (hal. 100, paragraf 3-4). Meskipun tampak lepas-kendali dari jalan cerita, namun sesungguhnya, bahagian paragraf itu sedang menginterupsi pembaca dengan cara menegaskan bahwa tokoh “aku” sedang menuliskan “cerita”.
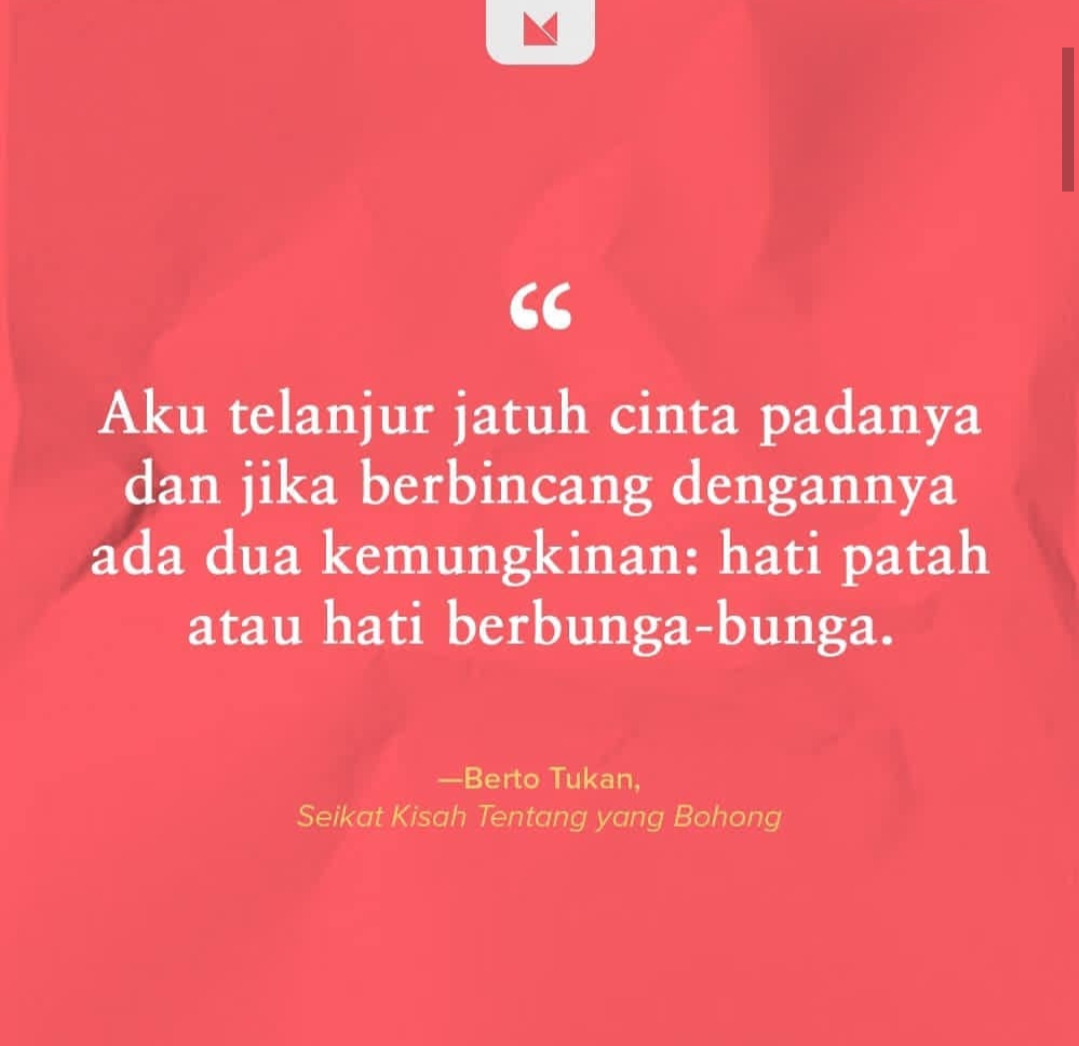
“Aku” itu bisa saja pengarangnya sendiri. Dalam cerita pendek yang sadar-diri dan tidak ambisius untuk menjadi “realitas objektif”, kehadiran pengarang dalam cerita yang dibuatnya sendiri adalah tidak masalah sama sekali, bahkan jamak dilakukan. Dengan hadirnya pengarang dalam cerita justru semakin memperkuat ke-fiktif-an. Bahkan, cerita yang seperti itu pada taraf tertentu sedang berusaha menunjukkan cairnya batas antara yang nyata dengan yang fiktif. Atau suatu penekakan bahwa dalam yang nyata selalu ada yang fiktif. Begitu juga sebaliknya, dalam setiap yang fiktif senantiasa ada retakan untuk melihat yang benar.
III
Apakah dalam buku Seikat Kisah tentang Yang Bohong ini, seberapapun buku tersebut menegaskan ke-fiktif-an dirinya, tak ada sama sekali “kebenaran”?
Beberapa tempat dalam kisah tersebut adalah tempat yang bisa kita cari rujukannya di dunia-nyata. Namun, bukan aspek kesamaan seperti itu yang semata-mata membuat buku ini mempunyai “hubungan langsung” dengan kenyataan, melainkan aspek “seikat” yang ditekankan dari judul buku itu sendiri. Oleh sebab itu, beranjak dari kata “seikat” tersebut, tak ada salahnya kita perjelas ikatan itu dengan sebuah imajinasi: Kita bayangkan 17 cerita di dalamnya sebagai 17 kejadian yang terjadi dalam waktu yang tak jauh berbeda, misalkan pada hari yang sama, di Indonesia.
Maka, melalui buku ini, kita bisa melihat sebuah lanskap kehidupan sosial dalam suatu struktur masyarakat Indonesia, dengan berbagai latar tempat, seperti kota dan desa, pinggiran dan pusat, dst. Beberapa kisah bercerita tentang cinta, tapi kisah cinta yang berbeda modus dan walaupun banyak kisah tragis maka kita akan mendapatkan ketragisan yang tak sama. Banyak penggambaran atas kondisi rakyat bawah tetapi rakyat bawah tersebut digambarkan tidak sedang “memikirkan” hal yang sama. Dan seterusnya.
Dengan bantuan imajinasi atas “yang seikat” tersebut, paling tidak, buku ini membantu kita untuk mengingatkan sekaligus menegaskan kepada diri sendiri bahwa masyarakat kita sedang “sibuk” dengan problematika hidupnya sendiri-sendiri, meski “diikat” suatu kondisi kehidupan yang “sama” atau dalam suatu langkap kehidupan sosial di bawah suatu kekuasaan yang sama. Artinya, tidak semua orang bisa sedih, bahagia, terpukau, atau marah oleh hal-hal yang sama, meskipun bisa saja berbagai masalah yang dihadapi masyarakat tersebut disebabkan oleh hal-hal yang katakanlah tak jauh berbeda, seperti kemiskinan misalnya.

Itulah setidaknya “yang benar” dari sekumpulan “kisah bohong” ini. “Yang benar” di sini tentu saja bukan dalam pengertian bahwa ia benar-benar terjadi secara persis dengan apa yang dibahasakan dalam cerita. Tetapi, sesuatu yang mempunyai “relief” yang sama dengan kenyataan di sekitar kita. Bukankah kita, sebagaimana tokoh-tokoh cerita dalam buku ini, masih jauh dari suatu kesadaran bersama meski sebenarnya kita sebenarnya seikat?




