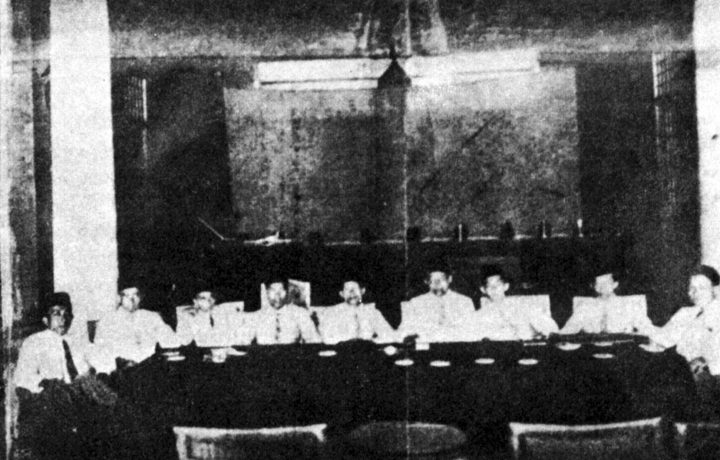Sering kita mendengar keluhan tentang matinya kritik sastra di lingkungan sastra Indonesia. Membicarakan kritik sastra, umumnya kita langsung teringat pada almahrum H.B. Jassin, walau tentu saja tidak hanya ia yang pernah bergelut di bidang itu. Ini lumrah adanya, sama seperti bila orang ditanya tentang puisi atau penyair Indonesia, kepala mereka langsung terarah pada Chairil Anwar.
Membaca dua artikel di lembaran Khazanah Pikiran Rakyat minggu-minggu lalu (Kritik dan Hama Sastra dan Seolah-olah Kritik Sastra) saya mendapatkan sebuah optimisme demikian; bahwa jika ada kritik sastra yang baik maka akan ada karya sastra yang baik. Stagnasi sastra terhindarkan dan kritik sastra memperkuat ‘keabadian’ karya sastra. Sebuah artikel ditulis oleh seorang penyair, satu lagi ditulis oleh seorang dosen sastra.
Ada baiknya kini saya menuliskan ihwal kritik sastra (anda bisa mengganti dua kata itu dengan uneg-uneg sastra) sebagai seseorang pembaca sastra yang tak rajin (hal ini benar adanya, saya tak serajin kebanyakan anda yang tak pernah absen membaca lembaran ini, pula lembaran budaya media lainnya). Identitas terkadang member legitimasi bukan? Ihwal penikmat sastra tak seheboh dan semeruah penikmat Liga Super Indonesia, kita semua maklum adanya.
***
Di sinilah letak soalnya saya kira, mengapa penikmati sastra tak seramai penikmat Liga Super Indonesia. Kenyataan bahwa tingkat melek baca di negeri ini masih jauh dari yang diharapkan, adanya kita sudah paham. Namun apakah jawaban itu melapangkan dada ketika banyak mahasiswa-mahasiswi yang lebih memilih menyisihkan uangnya untuk membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Uruguay atau tiket masuk Java Rockin Land demi menyaksikan The Smashing Pumpkins, ketimbang menghabiskannya untuk sejam dua jam berkeliling di pameran buku? Mari kita kembalikan masalah ini pada pangkuan sastrawan dan kritikus sastra.
Jika memang kritik sastra membantu ‘mengabadikan’ karya sastra dan atau menghindari stagnasi karya sastra, jelas jarang ada (anda boleh menggantinya dengan tak pernah ada) kritik sastra di Indonesia ini. Bukankah karya yang kita kenal ‘mengabadi’ adalah kanon dengan perspektif berlandaskan ideologi tertentu? Apakah kritik berprespektif tertentu yang mengesampingkan karya lain yang tak masuk dalam perspektifnya masih mau kita junjung tinggi? Bukankah setiap disiplin ilmu itu pada hakikatnya berguna? Jika ia tak mencapai guna yang dikehendaki darinya, masihkah perlu kita menganggap dia ada?
Anggaplah saja karya sastra itu tesis dan kritik sastra itu antithesis, maka kita tentu mencari darinya sebuah sintesis baru. Namun jika keduanya kokoh pada posisi masing-masing, kapankah ada sintesis itu? Atau jika karya sastra itu benda yang perlu ditransfer dari sang produsen pada konsumennya, apakah kuratorial yang dilakukan atasnya sudah berhasil? Saya rasa, kuratornya masih mencari-cari cara terbaik untuk menjalankan fungsinya secara penuh.

Atau jangan-jangan sang konsumen lebih ingin tanpa melalui sang kuratornya? Dia mau langsung terjun ke dalamnya, menjelajahinya, dan keluar dengan pemahaman dan intisari yang didapatkannya, menutup mata terhadap segala keinginan dari sang produsen dan sang kurator yang duduk diam di sana. Saya kira yang terakhir inilah yang lebih baik dan anda memang bebas menentukan pendapat anda sendiri untuk hal ini.
Ah yah, setelah berpanjang lebar di atas sana, saya kini sadar pada kesalahan saya, bahwa segala yang ada di dunia saat ini adalah sastra. Lagu, iklan, film, peringatan pemerintah pada bungkus rokok, stiker dari pengurus RW yang ada di pintu rumah anda, semuanya sastra. Dan di saat anda menikmati sastra, anda juga bayar pajak.
***
Sang penggerak yang menggerakan kedua essei yang judulnya telah saya kutipkan pada awal tulisan ini adalah buku Darah Daging Sastra Indonesia, yakni metaphor tentang hama sastra yang dipakai Damhuri Muhammad. Sungguh, saya salah satu yang tergerak mencari buku itu setelah membaca kedua essei tersebut. Saya tentu saja tidak akan masuk lagi pada masalah hama tetumbuhan sastra itu. Namun cover buku yang menekankan ketajaman pena mampu menembus daging dan mengucurkan darah dari dalam tubuh sungguh sesuatu yang menggetarkan. Saya belum membaca secara penuh isi buku tersebut. Maklumlah, menentukan menggunakan sandal atau sepatu ketika kita hendak keluar rumah pun sudah merupakan sebuah olah otak tersendiri yang butuh waktu tertentu pula.
Namun saya sudah membaca daftar isinya. Banyak artikel di sana dan semuanya dibagi dalam empat bagian. Lantas, ketika sampai di kalimat ini, saya teringat pada ihwal perbedaan penikmat sastra dan penikmat Liga Jarum Super yang tadi sudah saya bahas. Dari pengelompokan essei-essei tersebut, nyatalah bahwa soal penikmat itu tak disinggung. Semoga saya akan meralat kalimat ini ketika saya membaca buku tersebut dengan lebih serius dan secara keseluruhan. Pantaslah bila kedua essei yang saya sebutkan di atas berbicara ihwal karya sastra dan atau sastrawan dengan kritik sastra dan atau kritikus sastra. Ah, saya merasa sia-sia mengetik di depan komputer. Namun, sudahlah. Tak penting juga untuk dipertimbangkan. Toh, pembaca menerima apa yang sudah tersaji tanpa perlu pusing memikirkan bagaimana di dapur sana sastrawan menyediakan hidangan, dan bagaimana daftar menu itu dihias sedemikian rupa.
Darah daging mengingatkan kita pada tubuh. Tubuh tentu punya jiwa. Mungkin jiwa sastra ada pada pembaca, mungkin. Atau jiwa sastra ada pada kehidupan. Atau jiwa sastra ada pada perpaduan dari tetek bengek kehidupan sehari-hari, sastra yang mengestetikannya, dan kritik atasnya. Dengan kata lain, bila semua kita bisa melakukan tiga hal itu bersamaan.
*Catatan: Tulisan ini dipublikasikan di blo lama saya pada 16 November 2010.