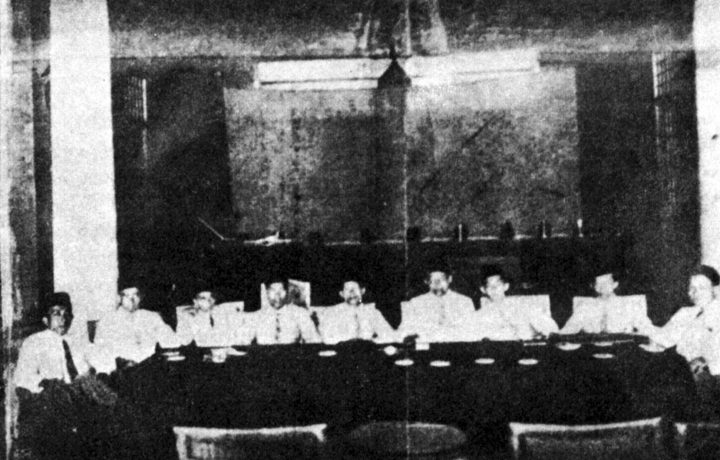Perihal karya sastra yang mengangkat sejarah kembali muncul beberapa waktu lalu dengan esai Binhad Nurrohmat (BN) dan Ahda Imran (AI) (Kompas, 11 dan 18 November 2012). BN antara lain mempertanyakan apakah para penulis novel sastra hendak menjadi sejarahwan atau novelis? Sedangkan Ahda Imran setangkapan saya melihat fenomena novel sejarah sebagai sebuah fenomena tuntutan pasar. Berawal dari perbincangan dalam Borobudur Writers Festival beberapa waktu lalu, kedua esai di atas dalam pandangan saya membawa kita untuk lebih tersadar ketika berada di pajangan buku di sebuah toko buku dan menemukan di sana, entah dari dalam negeri mau pun luar negeri, novel-novel yang mengangkat cerita sejarah, tak jarang dengan judul dan cover yang bombastis.
Tentu kita tak perlu mengungkit lagi perkara ‘kejujuran akademis dan sastrawan’ seperti yang tersirat pada tulisan BN. Kita andaikan saja di sini, sastrawan dan sejarahwan kita menjalankannya. Itu berarti kebenaran metode (untuk sejarahwan) dan kebenaran realitas cerita (untuk sastrawan)—lantaran setiap karya sastra yang mengangkat setting yang aktual dan dapat dicek, ada baiknya mengatakan sebenar-benarnya ia—tak perlulah kita perdebatkan lagi. Dengan demikian, kekahwatiran BN bahwa sastra sejarah yang tak baik akan berdampak ‘buruk’ pada masyarakat dengan sendirinya hilang.
Pintu Sempit Sastra Sejarah

BN dalam tulisannya mengungkapkan bahwa sastra sejarah mampu menceritakan sejarah dengan lebih baik bagi khalayak banyak dibandingkan, misalnya, sebuah hasil penelitian sejarah. Novel tentang sejarah kehidupan Gajah Mada akan lebih enak dan mengena bagi khalayak banyak dibandingkan dengan sebuah buku akademis sejarah tentang subyek yang sama. Ini lantaran sastra mampu memberi nilai estetik pada fakta-fakta sejarah dan yang estetik inilah lebih berterima pada khalayak banyak. Dengan demikian maka bisa saja fungsi sastra di sini hanya sekadar memberi darah dan daging serta kelenturan pada fakta-fakta sejarah yang ditemukan para akademisi sejarah. Sastra(wan) hanya pendaur ulang yang sedikit lebih kreatif; semacam perias yang hanya menambahkan satu dua hal sehingga lebih menarik.
Tentu tak sesederhana itu kehendak sastra, apalagi jika memang ada sastrawan yang melakukan riset untuk karyanya dan menemukan hal-hal yang luput oleh sejarahwan. Lagi-lagi, kita andaikan dulu perkara metode penelitian sudahlah selesai. Tetapi itu pun tidak membuat sastra sejarah punya fungsi yang berbeda dengan sejarah sebagai ilmu, kecuali hanya sebagai perias fakta sejarah. Sebuah peristiwa sejarah yang besar, Perang Bubat misalnya, di rak buku sebelah kanan ada buku sejarah tentangnya karya seorang sejarahwan dengan bahasa yang kaku dan tidak pejal dan di rak yang lainnya ada novel tentang Perang Bubat karya seorang novelis dengan bahasa yang lentur dan pejal. Sebuah novel tentang Gajah Mada hanya akan lebih indah penuturannya ketimbang sebuah buku sejarah tentang Gajah Mada yang kaku dan tak indah.
Lantas, jika ada seorang sejarahwan dan atau sebuah buku sejarah yang bisa menuliskan fakta-fakta sejarah dengan estetik dan hidup, hendak lari ke mana dan berpegang pada fungsi manakah sastra jika demikian? Apakah pembedanya hanya pada label, ini buku novel sejarah dan ini buku ilmiah sejarah? Sungguh sayang jika demikian, lantaran sastra seperti tak ada artinya. Problem ini bisa muncul lantaran kecenderungan sastra sejarah untuk mengangkat tema-tema besar, mengangkat kisah para pahlawan, sebagaimana dilakukan sejarah mainstream dalam rangka, seperti yang diutarakan AI, memberi rasa pede pada kekinian yang memang tengah amburadul. Apalagi, penyuntikan rasa percaya diri pada kekinian dengan menceritakan kembali kebesaran masa silam dengan segala pahlawan yang hampir setengah dewa itu pun bermasalah lantaran ia diam-diam membisikan bahwa kebesaran sejarah dimungkinkan dan diciptakan oleh para pahlawan dan mereka yang terpilih saja.
Di sini, sesungguhnya sastra sejarah diberi kesempatan untuk merefisi itu dan memberi kepercayaan pada khalayak ramai yang menurut BN lebih bisa menerima sejarah melalui sastra; sebuah kesempatan sempit namun dimungkin karena imajinasi adalah milik sastra.
Menceritakan yang Tak Tercatat
Sejarah memanglah salah satu penjelas tentang manusia, dunianya, dan keberadaannya di dunia ini. Menceritakan kembali sejarah untuk kepentingan hari ini dan proyeksi masa depan dengan demikian penting adanya. Tugas ini pertama kali memang dipanggul oleh sastra. Ingat bahwa sejarah pertama-tama diwartakan melalui sastra dalam rupa dongeng dan mitos-mitos. Ketika sejarah menuliskan fakta-fakta sejarah dengan caranya sendiri yang lebih ‘ilmiah’, tentulah kurang elok bila sastra hanya mengambil celah merias wajah kaku fakta sejarah. Apalagi ketika sejarah di Indonesia beria-ria dengan sejarah-sejarah kanon nan megah; Gajah Mada, Majapahit, Piramida, dan pula Atlantis. Sastra terasa kurang greget-nya ketika juga menceritakan segala yang meriah dan megah tersebut; sastra dan sejarah lantas hanya sebagai pil pengobat “…guncangan yang mengganggu kekinian” (Ahda Imran, Kompas, 18 November 2012). Padahal, itu pun fatamorgana, lantaran sejarah yang demikian hanya menceritakan kepahlawanan orang-orang terpilih dan tidak pernah memberi tempat pada khalayak luas, mencatat silsilah keluarga istana tanpa menorehkan tanggal kelahiran tukang kudanya.
Berpihak pada khalayak luas dalam narasi-narasi sejarah yang besar dimungkinkan bagi sastra. Dengan imajinasi, sastra bisa menghidupkan mereka-mereka yang tak tercatat, menghidupkan mereka-mereka yang luput dari pena para pencatat kerajaan. Dengan demikian, segala fakta sejarah hanyalah sekadar latar dalam sastra sejarah dan sastra sejarah punya cerita-cerita yang tak mampu diendus sejarah yang akademis. Beribu sastra sejarah tentang masa Majapahit dan Gajah Mada bisa lahir dengan megisahkan mereka-mereka yang tak tercatat dalam narasi besar tanpa perlu menikahkan Diah Pitaloka dengan Hayam Wuruk misalnya.

Dengan menulis mereka yang tak tercatat dalam sejarah, sastra sejarah pun menyumbangkan cara pandang terhadap sejarah yang tidak terus terpaku pada tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa nan megah. Di sini juga imajinasi mendapat peran yang sangat besar dengan fakta-fakta sejarah, hasil kerja sejarahwan, sebagai alat bantu saja; bukan alat utama. Sejarah sastra lantas membuka kemungkinan-kemungkinan bahkan menghadirkan hal-hal yang tak sempat (atau tak mau) diungkapkan sejarah mainstream dan kanon. Sastra sejarah lantas juga menyadarkan khalayak pembacanya bahwa merekalah yang memungkinkan sejarah terus berjalan. Maka, pil untuk menyembuhkan kegoncangan akibat identitas yang dipertanyakan oleh kemajuan masa kini yang lebih mujarab bisa saja hadir. Sastra sejarah ada baiknya mengambil peran yang secara tersirat diimpikan Bertolt Brecht dalam sajaknya; “….Pada malam ketika Tembok Besar Cina selesai dibangun / Ke mana para kuli pergi?/ Roma Agung tumpah-ruah dengan gerbang kejayaan. / Siapa yang mendirikannya?/ Atas siapakah Caesar berjaya? Apakah Bizantium tersohor / Menyediakan puri-puri untuk seluruh penduduknya? / Bahkan dalam dongeng Atlantis, pada malam ketika samudra menerkam, / masih saja para Tuan menjerit-jerit memanggil budak-budaknya” (Bertolt Brecht, Pertanyaan-Pertanyaan Seorang Buruh yang Membaca).***
*Catatan: Tulisan ini dipublikasikan di blog lama saya pada 18 Mei 2013.