Bicara tentang puisi berarti bicara tentang sebuah jalan sunyi yang butuh ketabahan hati untuk melaluinya. Namun jalan sunyi ini, tanpa disadari, telah memasuki keseharian hidup manusia dewasa ini. Puisi hadir dalam berbagai penjelmaannya melalui media apa saja. Di radio, televisi, coretan-coretan di dinding, di buku-buku, bahkan dalam pembicaraan setiap hari, kita menemukan puisi. Puisi akan terus berubah dan, bagai bunglon, mampu beradaptasi dalam semua sisi kehidupan, seiring berkembangnya ibu kebudayaan.
Membaca tulisan F. Rahardi, Puisi dan Planet Bumi yang Kesepian, banyak hal yang bisa kita amini bersama dan banyak hal pula yang tak bisa kita amini begitu saja. Bagi Rahardi, ada atau tidak adanya puisi tak berpengaruh atas kehidupan di bumi. Dengan pernyataan demikian, Rahardi telah masuk pada dunia “andai-andai” yang tak bisa terlacak kepastiannya. Bagaimana kita memastikan penting atau tidak penting peran puisi, di saat penetrasi puisi telah masuk begitu dalam ke kehidupan manusia? Namun benar apa yang dikatakan Rahardi bahwa, puisi bukanlah bahan pokok kehidupan. Dan tak tersangkalkanlah bahwa, pamor puisi begitu jauh tertinggal dari sejawatnya yang lain semisal cerpen dan novel.
Hal yang paling tidak bisa saya setujui dari tulisan Rahardi adalah pengelu-eluan yang terlampau tinggi atas puisi. Rahardi bahkan men-just puisi-puisi yang bertebaran di majalah, koran, situs-situs internet dan di lomba-lomba baca puisi peringatan tujuh belasan sebagai sampahnya puisi. Sedangkan puisi yang benar-benar puisi menurutnya adalah puisi-puisi yang digunakan untuk memuliakah Allah. Dengan pengkotak-kotakkan seperti ini, Rahardi yang juga adalah penyair itu telah memiskinkan ruang lingkup dan meluasnya puisi. Ia juga dengannya telah membatasi penggunaan puisi, hanya pada beberapa tujuan saja. Lebih jauh lagi, dengan mengikuti pemikiran Rahardi tersebut, tersirat legitimasi berpuisi hanya untuk segelintir orang. Mereka yang percaya pada Tuhan bolehlah berpuisi, sedangkan yang tidak janganlah berpuisi.
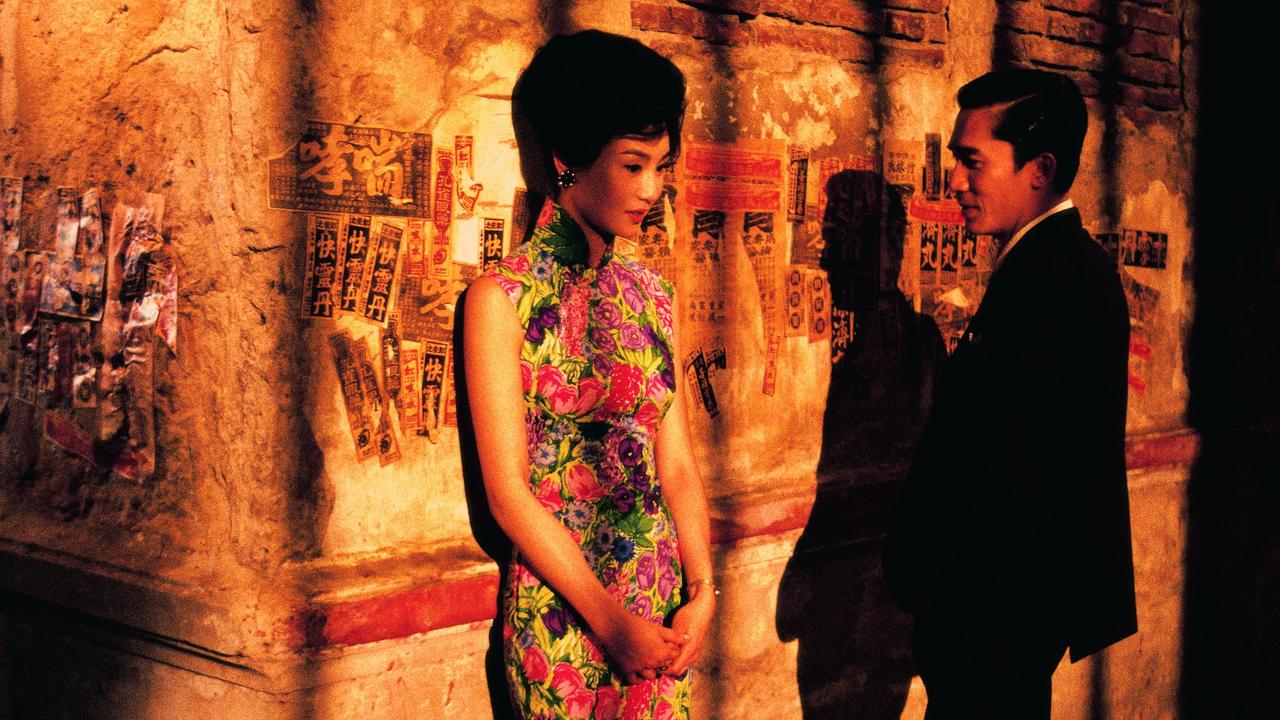
Selain itu, batasan apa yang digunakan Rahardi sehingga berkesimpulan bahwa, puisi-puisi, selain di tempat-tempat ibadah, adalah puisi-puisi sampah? Bukankah seiring berkembangnya kehidupan ini, (ingat, kita hidup di galaksi McLucan dan kami adalah generasi Y dengan perkembangan media berekspresi yang begitu banyaknya) puisi itu pun berkembang, bercecabang, dengan dahan-dahan aliran dan gaya yang berbeda-beda, dengan hukum estetikanya sendiri-sendiri? Sampai kapan puisi harus elitis tanpa bisa dijangkau kebanyakan orang nir-kecuali?
Satu lagi pandangan Rahardi yang patut diberi catatan yakni puisi sempurna adalah puisi yang lahir dari kehidupan (interaksi) manusia dengan suara alam. Sedangkan kehidupan manusia modern akan melahirkan puisi yang tidak sempurna. Alam dalam pengertian Rahardi adalah alam yang pure, alamiah, sesuai dengan konsep natur dalam naturalisme yang berkembang di Jerman beberapa dasawarsa lalu. Dengan demikian, ia tampak seolah-olah menutup mata akan alam yang telah begitu tercemar dewasa ini. Apakah dengan hidup di natur saja orang bisa bermeditasi, mengolah rasa, bercengkrama sendirian di dunia dalam? Apakah betul mereka yang ada di natur lebih bisa mengolah dunia dalam dari pada mereka yang ada di alam tercemar semisal Jakarta? Saya rasa tidak. Di mana saja berada, manusia bisa mengolah dan berinteraksi dengan dunia dalam-nya. Maka bagi saya, lahir di alam tanpa kebisingan bukanlah satu-satuya pasword untuk seseorang bisa bersyair, mencipta puisi sempurna. Semua betuk kehidupan, segala keadaan alam bisa menjadi puisi. Bahkan menurut hemat saya, alam yang hancur tercemar (alam modern?) lebih membutuhkan sentuhan penyair. Di sana, penyair bisa mengolah pengalamannya dengan dunia luar yang hancur berantakan, lantas diolah di dunia dalamnya untuk selanjutnya dilontarkan kembali pada khalayak dalam rupa puisi sebagai bahan refleksi komunal. Alam dalam rupanya seperti ini telah melahirkan Afrizal Malna, Binhad Nurohmat, Indra Tjahjadi dan masih berderet nama lagi yang karya mereka tak bisa serta-merta kita cap sebagai “sampahnya puisi”.
Rahardi juga menghimbau puisi untuk bersahaja dan tidak menjadi sarana pemrotes dan penggugat. Hal ini bisa dibaca sebagai ajakan pada penyair untuk hanya bermenung diri di kamar, sendirian, tanpa harus berinteraksi (sebagai penyair) dengan khalayak ramai. Puisi tak perlu menjadi senjata, begitu kira-kira maksud Rahardi. Seingat saya, puisi punya dua katagori yakni puisi kamar dan puisi mimbar. Rahardi agaknya membenarkan keberadaan puisi kamar ketimbang puisi mimbar. Para penyair pemrotes semisal Rendra dan Widji Thukul adalah para penyair puisi mimbar yang baik. Agaknya kurang adil bila mengatakan bahwa, puisi-puisi protes, puisi-puisi penuh teriakkan pemberontakan bukan puisi sebenarnya. Sebab yang sebenarnya adalah puisi-puisi bersahaja tanpa perlu berontak dan menggugat. Rahardi mungkin lupa, puisi seperti karya seni lainnya adalah cerminan kehidupan.
Puisi protes penuh gugatan merupakan puisi yang timbul dari kehidupan manusia termarjinal, manusia-manusia tertindas-terlupakan. Mungkin segala cara untuk terdengar tak berhasil dan puisi memberi jalan baru keselamatan. Bahasa puisi yang menggebu-gebu penuh protes, tidak bisa begitu saja dihakimi sebagai puisi tanpa isi, tanpa permenungan. Bukankah permenungan setiap orang akan menghasilkan hal yang berbeda-beda, begitu pula bahasa yang dilahirkan puisinya?

Mungkin ada baiknya saat ini kita mulai memandang puisi sebagai jalan sunyi yang dipilih mereka-mereka yang ingin menyepi. Mereka-mereka yang ingin berkontemplasi dengan cara kontemplasi yang berbeda-beda, dengan output masing-masingnya yang berbeda pula. Seiring mengkompleksnya dunia ini, mengkompleks pulalah mereka dan hal-hal yang hidup di dalamnya. Maka mungkin tak bisa lagi kita berpegang teguh pada definisi-definisi puisi lama yang muncul dari dunia yang tak sekompleks sekarang. Saya percaya, puisi akan tetap lahir selama manusia masih berpikir dan bernapas. Biarkan puisi dan jalan sunyinya membuktikan diri sebagai sebuah hasil kebudayaan yang bermutu. Ada baiknya kita tak memilah-milah mana yang baik mana yang jelek. Percayalah, yang bermutu akan bertahan di jalan sunyi itu dan yang tak bermutu akan tenggelam di tikungan jalan sunyi pertama atau pun tikungan kedua. Puisi adalah puzzle kecil dari kehidupan yang kompleks. Puisi pun menjadi kompleks dan beragam, seberagam dan sekompleks zamannya.
MarkasKata, Februari 2007
*Catatan: Tulisan bertarikh Februari 2007 ini pernah saya publikasikan di blog lama saya, kecoamerah, pada 6 Februari 2008. Tentunya lupa, tulisan ini dalam rangka apa. Mungkin sekadar latihan saja kala itu.




