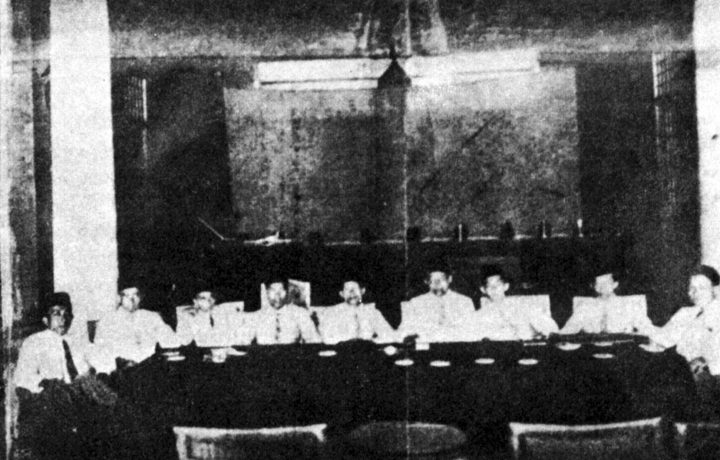Selama JIWA:Jakarta Biennale 2017 (selanjutnya disebut JIWA) berlangsung, di antara Hall A dan Hall B Gudang Sarinah Ekosistem, tersaji sebuah kolam luas yang dipenuhi eceng gondok hijau tua yang diselang-selingi bunga-bunga berwarna emas. Indah dan enak dipandang.
Di malam hari, lelampu yang khusus dipasangkan di sekitar kolam itu semakin memanjakan mata. Sesiapa yang mendatangi tempat perhelatan utama JIWA ini akan ‘terganggu’ oleh kolam yang mencolok dan indah tersebut.
Tidak berlebihan bila kolam eceng gondok dengan bunga-bunga emas ini menjadi semacam ikon JIWA; sebuah gambaran yang agak sulit terlupakan pada pemirsa, setidaknya pada saya. Ia hadir pada mata saya, sebelum saya sempat menyaksikan karya-karya lain, atau bahkan membaca teks singkat kuratorial di tembok Hall B.

Analogi
Kolam eceng gondok hijau dengan bunga-bunga emas itu adalah karya Siti Adiyati. Karya ini pertama kali hadir pada 1979 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta dalam rangka pameran kedua Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia. Tentu saja sulit bagi saya membayangkan, apakah kehadirannya kala itu semencolok kehadirannya di Gudang Sarinah Ekosistem.
Setidaknya, Agus Dermawan T di Harian Kompas, 22 Oktober 1979 mencatat, “sementara itu Siti Adyati Subangun hadir antara lain dengan daun-daun eceng gondok berbunga emas. Daun-daun tersebut daun benar-benar yang diletakkan di dalam kolam kecil yang khusus dibuat dalam ruang pameran itu. Tak hanya nilai karikatural yang bisa tertangkap, tapi juga nilai artistik yang diungkapkan oleh aksentuasi warna tumbuhan tersebut“.
Karikatural yang dimaksud Dermawan T barangkali adalah hadirnya tumbuhan eceng gondok di ruang pameran. Setidaknya, pada tulisan yang saya kutip di atas, tidak ada keterangan lebih lanjut perihal itu. Kekarikaturalannya ini bisa kita tarik lebih jauh.
Pada JIWA, kolam eceng gondok diperbesar menjadi 20 x 8 meter dengan kedalaman air 30 cm. Megah, indah, mencolok.
Sebagai pemirsa karya seni yang baik, tentu kita tidak berhenti pada ‘gangguan’ visual sebuah karya semata. Pertanyaan kita lebih lanjut adalah apa yang melatar-belakangi kehadiran karya ini pada 1979 maupun 2017?
Karya ini rupanya hadir sebagai analogi ketimpangan sosial masyarakat. Pada katalog JIWA dikatakan eceng gondok adalah “…metafora parasit kehidupan yang berbiak tanpa kendali“. Metafora itu terejawantah pula pada pilihan materialnya.
Eceng gondok pada JIWA diambil dari empang di sebuah real estate terkemuka di Jakarta Utara (2017). Sedangkan eceng gondok karya pada 1979 diambil dari daerah Kalipasir, Jakarta Pusat yang banyak dihuni kelas menengah ke bawah.
Jika latar belakang eceng gondok demikian, maka bunga-bunga plastik emasnya adalah barang mahal. Pada 1979, setangkai bunga mawar plastik itu setara sekilo beras. Kini, pada 2017, satu tangkai bunga itu seharga 3 kilogram beras raskin.
Mengatasi Kesementaraan

Melihat latar belakang materialnya yang demikian, saya lantas terhenyak pada judul karya yang terdengar merdu di telinga itu, Eceng Gondok Berbunga Emas. Judul ini barangkali pada pandangan pertama terlihat seolah hanya mendeskripsikan tampakan fisik karya tersebut.
Namun, justru judul inilah yang mempertajam ironi. Bagaimana mungkin eceng gondok bisa berbunga emas?
Ada sebuah utopia pada judul itu, seutopia judul-judul sinetron televisi kita. Tukang Bubur Naik Haji misalnya.
Bukankah eceng gondok itu tumbuhan murah yang tak ada di dalam kelas tetumbuhan mewah atau sayuran-sayuran wah? Jika ia bisa berbunga emas, simbol dari kekayaan, bukankah itu semacam keberuntungan, sebuah mujizat yang baru bisa terulang 100 Abad kemudian? Dengan kata lain, mustahil eceng gondok bisa berbunga emas.
Namun, toh ada eceng gondok berbunga emas; dan ia ada di JIWA. Di sinilah metafora yang lain lagi bermain di dalam karya Siti Adiyati ini.
Pertama, eceng gondok diambil dari wilayah masyarakat miskin (Kalipasir pada 1979) atau wilayah yang dibangun di atas ketergusuran rakyat miskin (real estate pada 2017). Pembangunan real estate dalam konteks pembangunanisme bisa dibaca sebagai sebuah peristiwa yang menyingkirkan, atau minimal tidak memberikan akses, pada masyarakat miskin.
Sedangkan, kedua, bunga emas, dari perbandingan harganya dengan beras di atas, sudah jelas menyimbolkan masyarakat kelas berada.
Dari juxtaposisi antara eceng gondok dan bunga emas ini kita bisa membayangkan kenyataan berikut; ‘keberadaan masyarakat berada ditopang oleh masyarakat miskin’.
Di dalam ilmu sosial kita tahu, bahwa masyarakat miskin menjadi miskin untuk membuat golongan kaya menjadi kaya atau tetap kaya. Dan perbandingan antara masyarakat miskin dan golongan kaya selalu lebih banyak masyarakat miskinnya dari pada golongan kaya; dari 1.000 penduduk misalnya, 100 orangnya golongan kaya dan sisanya kaum miskin.
Hal terakhir itu pun dimetaforakan pada oleh Eceng Gondok Berbunga Emas. Lihat saja perbandingan eceng gondok dan bunga emas pada karya itu. Persis di titik ini, Siti Adiyati dengan begitu sederhana berhasil menggambarkan ironi masyarakat kita–yang juga tidak berubah keironisannya dari 1979 hingga kini–dengan menggugah dan indah. Kesederhanaan ini tampak pula pada pilihan bahasa judulnya.
Bersamaan dengan itu, pantas betul karya ini dihadirkan kembali oleh JIWA setelah 38 tahun. Bukan hanya perihal pentingnya karya ini di dalam sejarah seni kontemporer kita. Lebih dari itu, ketepatannya menggambarkan ironi masyarakat dan kemampuannya mengatasi kesementaraan. Jika Eceng Gondok Berbunga Emas tak mampu mengatasi kesementaraan, maka ia tak relevan di 2017.
Jika anda punya waktu untuk memeriksa tagar #jakartabiennale2017, anda akan menemukan foto beberapa pemirsa JIWA yang berswafoto pada Eceng Gondok Berbunga Emas. Pada karya dengan keironisan dan metafora yang menyedihkan demikian itu, swafoto-swafoto yang dihasilkan penuh dengan keceriaan. Ini sebuah ironi lain lagi.

Dan saya tentu punya kebebasan untuk menganggap wajah-wajah ceria pada swafoto-swafoto itu sebagai ketabahan hati menghadapi hidup yang penuh ironi ini atau kekebalan hati hidup sebagai bunga-bunga emas.
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Beritagar.id pada 26 November 2017.