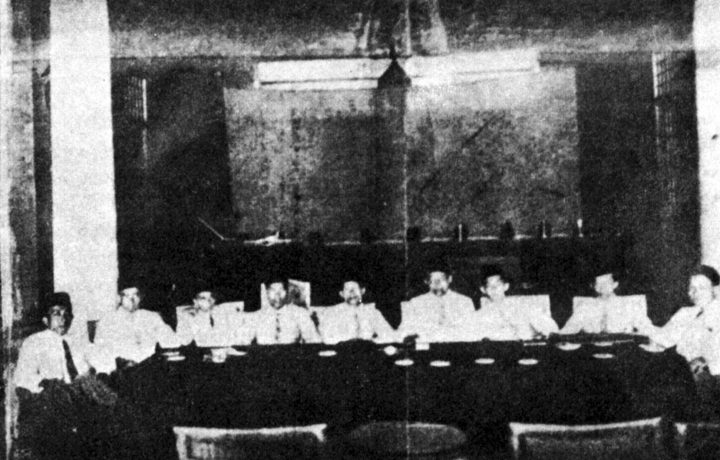Beberapa hari yang lalu saya sempat curi-curi dengar perbincangan antara dua orang. Keduanya sepertinya punya profesi yang sama; entah pengantar barang, entah petugas logistik perusahan tertentu, atau apalah. Sebenarnya tak penting-penting amat apa profesi mereka sebenarnya. Yang terpenting adalah dua tiga kalimat yang sempat saya dengar dari mereka. Mereka tengah berbicara kemungkinan profesi lain yang harus mereka jalani karena dengan kemunculan aplikasi-aplikasi yang memudahkan orang melakukan banyak hal, kemungkinan profesi mereka sudah tidak dibutuhkan lagi.
Memang, dengan menjamurnya smartphone sekarang ini, banyak aplikasi bisa kita unduh dan aplikasi-aplikasi itu memudahkan sungguh kehidupan kita. Baru saja kemarin petang di Halte Busway Dukuh Atas, saya disamperin oleh SPG yang menawarkan aplikasi Trafi, sebuah aplikasi yang memungkinkan kita mendapatkan rute angkutan umum dan jadwal yang dikatakan cukup presisi. Setiap aplikasi dengan kemampuan ‘mengerjakan’ hal-hal yang sebelumnya membutuhkan sedikit effort manusia ini—untuk kasus trafi, kita butuh usaha bertanya untuk mengetahui rute dan jadwal—minimal akan mengubah kebiasaan manusia dan lebih radikal lagi menghilangkan profesi tertentu. Fenomena ojek online yang kini menjelma kebutuhan tak terpisahkan masyarakat urban adalah contoh paling nyatanya. Anda bisa mencari sendiri apa-apa yang hilang dan apa-apa yang muncul dari fenomena tersebut. Dengan kata lain, setiap perubahan pada teknologi—yang sifatnya menunjang hidup manusia—pastinya akan mengubah cara hidup dan juga profesi—atau mekanisme profesi tertentu—dari manusia.

Bagi saya, bukan perkara teknologi itu segitu jahatnya sehingga membuat manusia harus kehilangan pekerjaannya. Sisi humanis manusia yang kerap menjangkiti hati-hati berbelas kasih kelas menengah Indonesia ini memang pada pandangan pertama terkesan kritis. Tetapi jika diperiksa lebih jauh, dia menyimpan kenaifan berpikir. Permasalahannya, pada pokok awal, teknologi adalah cara manusia menanggulangi hidupnya di tengah alam yang kerap membatasi ruang gerak manusia. Di dalam sejarah peradaban, kita mengenal begitu macam penemuan teknologi yang begitu membantu hidup manusia di kemudian hari. Penemuan api adalah juga penemuan teknologi yang sangat spektakuler tentu saja di zamannya. Begitu juga penemuan-penemuan perkakas sehari-hari yang barangkali remeh temeh bagi kita di masa sekarang. Bisa jadi, pada suatu ketika di hari kemudian, penemuan smartphone lantas aplikasi-aplikasi ikutannya bisa juga dipandang seremeh temeh kita memandang api sekarang.
Kenyataan bahwa ada yang tersingkir karena ditemukannya teknologi, sesederhana ditinggalkannya cara-cara hidup lama yang berganti cara hidup baru yang lebih dipermudah berkat adanya teknologi. Permasalahannya, dalam konteks zaman kita sekarang yang berbeda dengan zaman penemuan api, adalah adanya sistem kapitalisme yang membuat ada segelintir orang menguasai penggunaan teknologi-teknologi tersebut. Ambillah contoh orang-orang yang kehilangan pekerjaan tadi. DI satu sisi, mereka kehilangan pekerjaan namun di sisi lain ada perusahan-perusahan tertentu yang mengeruk keuntungan besar dari penggunaan-penggunaan aplikasi tersebut. Berbeda dengan era penemuan api yang tidak diikuti oleh monopoli pihak tertentu terhadap api (atau memang ada pada zamannya ?). Masalah seputar bagaimana agar monopoli itu tidak terjadi, tentu bukan tugas tulisan sederhana ini. Anda bisa mencarinya di buku-buku kiri pada toko online terdekat di aplikasi media sosial anda. Tentu saja diandaikan anda juga punya cara baca yang benar.
***
Dengan demikian, tidaklah sulit untuk mengatakan bahwa keberadaan smartphone beserta segala turunannya tadi, sebagai sebuah fenomena perubahan teknologi, bukanlah baru-baru amat. Di dalam sejarah, hal ini kerap terjadi. Sebutlah perubahan-perubahan besar seperti revolusi industri pada abad XVIII yang mengubah sistem ekonomi manusia. Lantas, ia diikuti oleh perubahan di ranah kebudayaan pada awal abad XX.

Awal abad XX, teknologi yang tadinya mengubah begitu sangat ekonomi manusia melalui revolusi industri mengalami modifikasi lebih lanjutnya dan merambah ke ranah kebudayaan aka kesenian. Mesin-mesin yang tadinya memproduksi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam jumlah banyak secara mekanistis, sistem kerjanya masuk ke ranah penciptaan-penciptaan kesenian. Muncullah film, fotografi, dan juga teknologi perekaman musik. Dari ketiga itu, dilihat dari sistem kerja penciptaan berdasarkan tawaran teknologi baru ini, yang paling baru dan tidak ada perbandingan langsungnya di masa lalu tentulah film lantas diikuti oleh fotografi. Perekaman musik jauh lebih dekat dengan masa lalunya yakni pertunjukan musik secara langsung. Di dalam perekaman musik, pemusik-pemusik konfensional tetap bermain musik secara konfensional, direkam, lantas hasil rekaman diperbanyak. Jadi, unsur performatif dari musik tetap diandaikan di dalam perekaman musik. Hal ini berbeda dengan film dan fotografi yang lebih minimal dalam menggunakan hal lama di dalam penciptaannya.
Nah, tentu saja tidak terlalu rumit untuk membayangkan adanya keresahan-keresahan di kalangan mereka yang berkecimpung di ranah musik kala itu. Dari keresahan-keresahan ‘cetek’ semacam ‘ke mana mereka-mereka yang selama ini hidup dari bermain musik untuk publik jika peran mereka diganti oleh gramaphone’ misalnya hingga pertanyaan ‘serius’ semacam ‘di mana originalitas sebuah musik jika ia bisa digandakan sebanyak-banyaknya’. Unek-unek semacam itu salah satunya kita temukan di dalam “The Menace of Mechanical Music”-nya John Philip Sousa, seorang konduktor musik klasik asal Amerika. Tentu saja banyak hal dibincangkan Sousa di dalam tulisannya itu. Namun saya kira, dua hal di atas cukup mewakilinya.
Untuk keresahan pertama perihal kemana para performer musik pergi jika peran mereka digantikan oleh alat pemutar musik, saya kira kita semua sudah tahu belaka, tidak beralasan. Sampai hari ini, live performance musik tetap punya tempat dan tetap digandrungi hingga hari ini. Pertanyaannya justru pada apakah produksi rekaman musik dalam jumlah yang tak berhingga menunjang atau mengkerdilkan live performance-nya? Eropa abad XVIII musik hanya didengarkan di gereja dan di beberapa kegiatan tertentu, kerapnya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kaum ningrat. Orang kebanyakan tidak punya kesempatan untuk mendengarkannya. Dengan adanya teknologi rekaman, musik bisa didengarkan secara privat, di mana pun. Apalagi saat ini yang penggandaannya tidak lagi secara fisik tetapi hanya butuh sebuah smartphone untuk mendengarkannya.

Simpulannya jelas; teknologi rekaman musik mendemokratisasi penikmatan atas musik. Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak orang pula yang bisa mendengarkannya. Kalau mau memasukkan juga unsur kapitalisasinya maka semakin banyak jumlahnya tersedia, semakin murah pulalah ia. Saya kira, semakin banyak orang yang mendengar versi rekaman, maka semakin banyak orang pula yang mengenal secara tak langsung sosok di balik musik yang didengarkannya. Manusia tetap sadar bahwa apa yang ia dengar adalah rekaman dan manusia tetap menyimpan sensasi untuk bertemu langsung dengan mereka yang berada di balik rekaman itu. Maka, teknologi rekaman musik sebenarnya lebih membuka peluang pada performance musik.
Namun, keresahan pertama di atas ini memang kerapnya dianggap cetek dalam perbincangan perihal estetika dan keartistikan. Seolah-olah, perbincangan yang menyerempet ke arah ekonomi ini bukan permasalahan estetika dan keartistikan. Otentisitas, keresahan kedua di ataslah, yang kerap dianggap permasalahan estetika dan artistik. Salah satu pemikir yang menjawab hal ini adalah Walter Benjamin. Jika Soussa menulis “The Menace of Mechanical Music” pada 1906, Benjamin menulis “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” pada 1935, jauh setelah Soussa resah.
***
Bagi Benjamin pada dasarnya sebuah karya seni adalah penggandaan atas sesuatu yang lain di luar dirinya. Lagu adalah penggandaan atas bebunyian alam oleh seorang komposer. Begitu juga karya seni lainnya. Dengan teknologi perekaman, mekanisme penggandaan yang dulunya tersirat dibikin lebih tersurat dan nyata; diradikalisasi. Narasi otentisitas sebuah karya seni justru muncul lantaran sifat dan jumlah karya seni yang tunggal ketika belum mengenal teknologi penggandaan mekanisnya. Pengalaman penikmatannnya pun bersifat tunggal dan tak bisa diulang. Seniman menjelma sosok yang sulit dijamah lantaran karyanya sulit dinikmati; butuh akses dan waktu tertentu untuk menikmatinya.
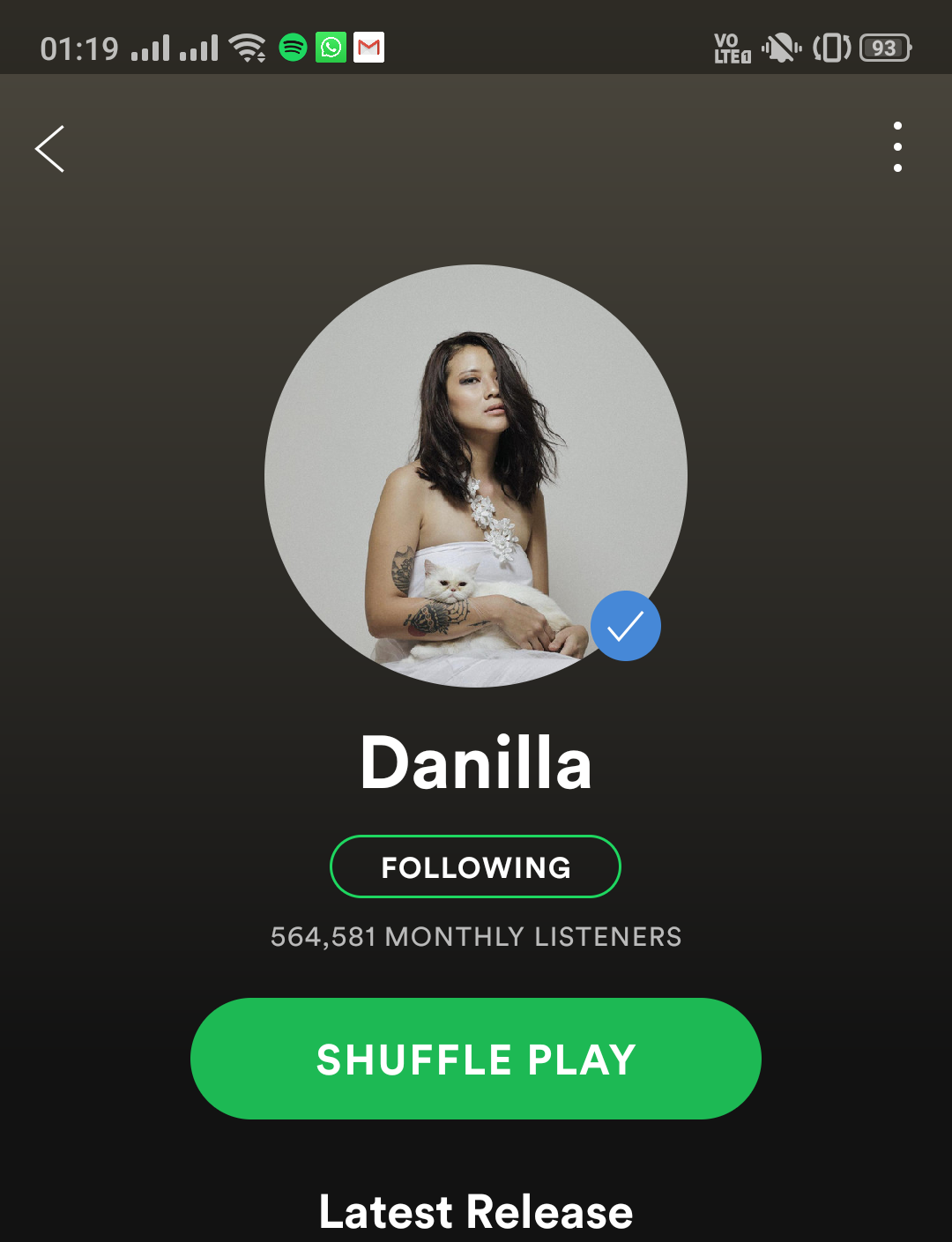
Akibat bersifat tunggal dan sulit dijamah itu, penikmatan karya seni pun menjelma sesuatu yang bersifat ritualistik. Hal inilah yang menurut Walter Benjamin dibongkar oleh teknologi reproduksi mekanis di dalam seni. Ketunggalan karya seni hilang maka turut bersamanya hilang pula kemagisan seorang seniman serta keotentikan karya seni. Yang muncul adalah jumlah yang banyak serta kemungkinan dinikmati siapa saja dengan efek yang berbeda-beda. Efek berbeda-beda ini bisa dirangkum dalam efek hiburannya. Dan yang perlu digaris-bawahi adalah kemungkinan demokratisasi penikmatan karya seni; sesiapa saja ‘punya kemungkinan’ untuk menikmati karya seni. Kenapa dikatakan punya kemungkinan, karena untuk sampai pada demokratisasi yang sungguh-sungguh, maka karya seni itu akan berbenturan dengan perihal ekonomi, dsb. Di sini, kita kembali lagi pada masalah yang disebutkan di awal tulisan ini; perihal monopoli atas karya seni.
***
Ketika menulis perihal kemungkinan demokratisasi penikmatan karya seni karena adanya teknologi reproduksi mekanis, Benjamin sadar sepenuhnya perihal monopoli ini. Kesadaran ini membawanya pada pembedaan atas budaya sinema Russia dan sinema Prancis aka Hollywood. Baginya, masyarakat harus menjadi faktor utama dalam penciptaan karya seni di era reproduksi mekanisnya. Dengan mengambil contoh praktik perfilman di Russia masa itu, Benjamin membicarakan potensi setiap orang untuk berkesenian yang mana ia juga menunjukkan hal yang sama pada kasus sastra atau teknologi cetak. Penonton tidak sekadar penonton yang membeo atas karya seni suguhan seniman, tetapi penonton punya otoritas sebagai seniman juga.
Lagi-lagi dengan mencontoh dunia film, aktor-aktor film di Russia tidak di dalam pengertian aktor pada dunia film Jerman atau Prancis kala itu, melainkan orang biasa yang memfilmkan diri mereka sendiri dan, bukan hanya itu, kerja dan keseharian mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan film di kebudayaan Eropa Barat di mana massa dikesampingkan di dalam produksi film. Lantas, beberapa cara digunakan oleh film di budaya ini untuk menjauhkan massa dengan strategi-strategi tertentu. Semua itu dilakukan dalam rangka, menurut Benjamin, mengkorupsi dan mendistorsi ketertarikan massa untuk memahami diri mereka sendiri dan kelas mereka melalui film (baca: seni).

Apa yang dihadapi Soussa dan Benjamin satu abad yang lalu sesungguhnya dalam bentuk yang lebih keras dihadapi kita saat ini. Andai Soussa hidup hari ini, unek-uneknya mungkin lebih banyak lagi. Reproduksi mekanis saat ini 1.000 kali lebih hebat dari era Soussa. Jika teknologi rekaman di masa Soussa masih mengandaikan pemusik yang memainkan musik lantas direkam, di masa ini, dengan menggunakan software tertentu dan aplikasi tertentu, siapa saja bisa membikin musik berbasis komputer. Betapa keresahan Soussa bisa berkali-kali lipat karenanya. Anda bisa mencari contoh pemusik atau grup musik yang terdiri dari orang-orang yang tidak mengerti cara mengoperasikan satu pun alat musik tetapi bisa membuat musik dengan bantuan komputer. Nah di tahap itu, ketika melihat unek-unek Soussa perihal otentisitas sebuah musik, bukankah sudah jauh panggang dari api? Barangkali benar, seniman perlu melihat kembali perannya; seniman yang terus membuat karya-karya adiluhung, atau seniman yang memfasilitasi masyarakat dan ‘berkarya’ bersama mereka?
Buka instagram Anda. Setiap hari, beribu-ribu gambar bisa Anda temukan di sana. Pada titik itu, masihkah perlu seorang seniman foto? Tunggu saja aplikasi semacam instagram ini merambah pada musik. Maka bisa dibayangkan setiap hari akan ada musik dengan durasi barangkai beberapa menit saja yang dibuat dengan sekali klik. Tunggu saja ketika aplikasi itu ada.
Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Jurnal Ruang (yang sepertinya sekarang sudah almahrum) pada 31 Mei 2017.